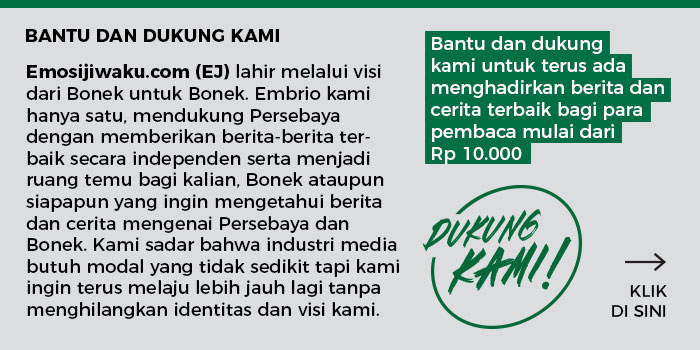Sebenarnya, aku malas menulis episode ini, tapi bagaimana lagi, aku sudah komitmen dalam hati mau berbagi pengalaman menjadi suporter Persebaya, menjadi Bonek (Lawas) mumpung sedang “Mood” untuk menulis, yah setidaknya sampai cerita tahun 2004.
Persebaya ke grandfinal, beberapa teman kantor segera mendaftar ke Jawa Pos ikut Tret-tet-tet ke Jakarta, antara lain aku, Syamsudin (alm), M. Zaini (alm), Nurhaman, Sahid, Supriyo (alm), H. Lilik, dan beberapa lagi, termasuk melengkapi diri dengan syal, topi, dan kaus ijo. Dengan seijin istri, aku pergi ke Jakarta dengan bus, entah berapa bus yang berkonvoi ke Senayan. Banyak sekali.
Sempat ada beberapa insiden pelemparan batu terhadap bus Jaya Utama yang kami tumpangi di sekitar Demak-Semarang, di malam hari, semua suporter yang sedang tidur terbangun kaget dan bus berhenti. “Sopo iku rek? kurang ajar!!!” Tapi sudah jelas, siapa yang menjadi tertuduh dalam insiden ini.
“Saking ae saiki bengi, nek awan ngono diuber maringono diajar ae sing sawat-sawat iki,” gerutu yang lain.
Di GBK, harus diakui, suporter Persebaya kalah jumlah dengan suporter Persib, dengan perbandingan sekira 35:65. Hal demikian sudah sewajarnya mengingat jarak Bandung-Jakarta hanya 4 jam, sedangkan kami harus menempuh 16 jam lebih, belum lagi suporter asli Jakarta yang kalah lawan Persebaya tentu berada di pihak lawan. Ini adalah kali kedua aku masuk stadion yang pernah menjadi yang terbesar di Asia itu, sebelumnya saat mendukung Persebaya 1987 melawan PSIS Semarang.
Pagi hari, koran-koran sudah memanas-manasi dengan memberi judul final ini sebagai “Perang Bubad” yang sebenarnya sangat “TABU” untuk diungkit karena menyangkut masa silam, ratusan tahun yang lampau, di mana diceritakan seluruh kontingen kerajaan Sunda-Galuh, dibantai habis pasukan Gajahmada di desa Bubad. Harusnya koran itu menahan diri.
Kalah jumlah sama sekali bukan hal yang mengkhawatirkan bagi segenap suporter Persebaya, koor saling ejekpun kami sanggup mengimbangi dengan kekuatan vokal yang setara.
Mereka mengejek (berbau SARA), “Jawa kowek!! Jawa kowek!!” maksud mereka Jawa kowe (kamu) dalam dialeg Tegal/Banyumas.
Spontan kami membalas, “Bandung taek!! Bandung taek!!” supaya sama-sama berakhiran ‘ek’ begitu seterusnya. Seru sekali.
Soal Suporter tidak jadi masalah yang dikhawatirkan hanya masalah non teknis yang biasa menghantui Persebaya sejak jaman old, yang sering menyebabkan Persebaya gagal.
Bencana itu begitu tiba-tiba datang ketika Subangkit mis komunikasi dengan kiper Putu Yasa, sehingga ball clearance yang dilakukan malah masuk ke gawang sendiri, suporter Persebaya terdiam sedih. Terjadinya gol yang tak diduga itu menyebabkan beberapa pemain Persebaya bermain keras untuk memancing emosi Persib. Tetapi, sudah ditakdirkan bahwa Persib malam itu mencapai peak performance-nya selama kompetisi ini.
Sebenarnya, aku melihat Persebaya bermain bagus, hanya saja ketertinggalan 0-1 menjadikan pemain tidak sabar, apalagi beberapa peluang yang seharusnya menjadi gol, terbuang sia-sia karena melenceng atau melambung. Salah satu yang kuingat adalah saat Budi Johanis mampu berliku-liku melewati para bek Persib, eksekusi Budi malah melambung diatas mistar kiper Persib, Sama’i Setiyadi.
Bahkan, pemain pengganti Persib, Dede Rosadi bisa memanfaatkan peluang untuk menjauh, Persib unggul 2-0 dan tidak terkejar lagi. Lemaslah kami semua.
Pertandingan belum usai, kami sudah hendak meninggalkan stadion, tetapi nyanyian olok-olok suporter Persib “Pulang, Marilah Pulang…” memancing emosi kami. Sahid, rekan sekerjaku, arek Menganti, terlihat mendekati pembatas kedua kubu, dia hendak menghajar salah seorang suporter lawan, tanpa takut sama sekali.
“Ayo cepet metu rek, aku gak sabar nek gak ngantemi musuh, ngene iki.” Katanya menahan rasa frustasi dan emosi. Aku tidak melihat Sahid lagi yang hilang di kerumunan penonton, tahu-tahu dia bercerita sudah menghajar seorang Bobotoh di luar stadion. Dia terlihat puas.
Semua wajah tampak lemas, kecewa dan putus asa, kami langsung menuju bus dan tidak ingin apa-apa lagi meski perut mulai lapar. Hanya satu yang kami inginkan, yaitu berkelahi.
Sayang tiada seorang pun yang bisa dijadikan lawan, semua di sekeliling adalah teman seperjuangan.
“Gak! Aku gak luwe…ngko ae,” kata Syamsudin, almarhum, ketika disodori nasi kotak.
Sepanjang perjalanan keluar Jakarta menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah, mataku sama sekali tidak bisa dipejamkan, dada terasa sesak, emosi memuncak dan suasana berkebalikan dengan saat berangkat, kini semua diam seribu basa, tidak satupun yang bergurau.
Temperamen keras dan dalam keadaan emosi yang tak tersalurkan, wajar saja bila esok harinya perjalanan bus tersendat-sendat, sering berhenti akibat bentrok dan mengejar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab (yang melempari bus). Yang melekat dalam ingatanku adalah ketika kami sampai di Demak. Di pinggir sungai tampak beberapa pemuda melempari bus kami dengan batu.
“Nah! Iki sing tak enten-enteni…” Begitu seru beberapa orang di antara kami, yang langsung bergegas turun.
Bus berhenti, suporter berhamburan mengejar pelempar tadi, pelempar itu memasuki sebuah sekolah dan kami mengejar sampai ke dalam. Tak pelak, bogem mentah mendarat di wajah pemuda na’as itu. Ibu-ibu yang melihat kejadian itu menjerit-jerit ketakutan. Tetapi ada sisi negatifnya, beberapa dari kita selesai menghajar, melakukan sesuatu yang bisa mencoreng nama baik (mengambil yang bukan haknya).
Di dekat bus, seorang pemuda tampak berdarah-darah dihajar suporter Persebaya, tetapi aneh, pemuda tersebut bukannya berlindung tapi seolah menantang, semakin remuklah dia, untung tiba-tiba datang seorang Kapten AD, langsung melerai, melindunginya dari amukan kami.
Aku tidak tahu, apakah lembaran ini patut ditulis atau tidak, tetapi itu yang aku alami sendiri.
Ketika aku harus masuk kerja lusa hari, beberapa rekan sekerja asal Malang mengolok-olok kami “Memalukan, kalah!!” kali ini mau tidak mau, aku harus menahan emosi. Kalau ini bukan kantor bisa jadi lain akibatnya, tapi mereka rekan sekerja yang sejak kami diterima bekerja diwajibkan memupuk jiwa kebersamaan, Jiwa Korsa.
Sementara rekan-rekan sekerja asal Jawa Barat, diam seribu basa. Tidak membahas laga final itu, dan aku paham apa yang mereka rasakan. Semuanya serba tidak enak. Bagiku, ini berlangsung beberapa hari, sumpeg peg peg!!
Padahal, bukankah menjadi juara II jelas lebih baik daripada Juara-III, IV dan selanjutnya, jauh lebih baik daripada tim-tim yang tersisih lebih dahulu. Tetapi entah kenapa, rasa sedihnya laksana tertimpa musibah besar. “Kalah di final bukan KIAMAT.” Masih ada hari esok, atau apakah Persebaya ingin juara terus menerus, yang lain nggak boleh???
Piala Dunia 1990 di Italia yang semarak, menjadi salah satu obat penawar luka, penglipur lara, apalagi tim kesayanganku Jerman, muncul sebagai Juara Dunia 1990 setelah mengalami dua kegagalan dalam final 1982 dan 1986.
Obat kedua penghapus duka adalah kelahiran anak pertamaku, seorang putri lucu, 7 Agustus 1990 di RS. Dr. Muhammad Saleh, Probolinggo.
Luka hati ini 95 persen sembuh ketika di akhir tahun, Persebaya Cilik yang diberi julukan “Bledug Ijo” mengukir prestasi mengejutkan, menjadi Juara Piala Utama dengan mengalahkan Pelita Jaya secara dramatis 3-2, setelah sebelumnya membabat Kramayudha Tiga Berlian 3-1, lantas menggasak Pupuk Kaltim 3-0 dan menundukkan PSM 2-1, lawan-lawan yang tidak mudah. Sayangnya nggak ketemu Persib.
Nama-nama tak dikenal langsung mencuat seperti M. Nizar, Hartono, Slamet Bachtiar, Yani Faturrachman, Winedy Purwito dipimpin oleh yang lebih senior seperti Yusuf Ekodono, Totok Anjik dan Machrus Afif.
Bledug adalah anak Gajah dalam bahasa Jawa dan Ijo nya sudah tidak usah dipertanyakan lagi. Sebutan ini (menurutku) sengaja dipakai dan diarahkan kepada mereka yang senantiasa nyinyir mengungkit sepakbola Gajah yang pernah dilakukan Persebaya, sebab sejatinya binatang Gajah tidak ada hubungan emosi sama sekali dengan Surabaya.
Gelar Bledug Ijo disematkan karena pemain-pemainnya masih sangat muda hasil regenerasi, dan kebetulan banyak yang bertubuh mungil semisal Yani Faturrahman, Winedy Purwito, Ali Zaini, dan sebagainya.
Bravo Bledug Ijo!!! lembaran yang harusnya hitam 1990 gagal menjadi hitam, dengan adanya kalian yang putih cemerlang. (bersambung)
*) Penulis: Eko Wardhana, Pensiunan BUMN yang tinggal di Sawojajar, Malang.