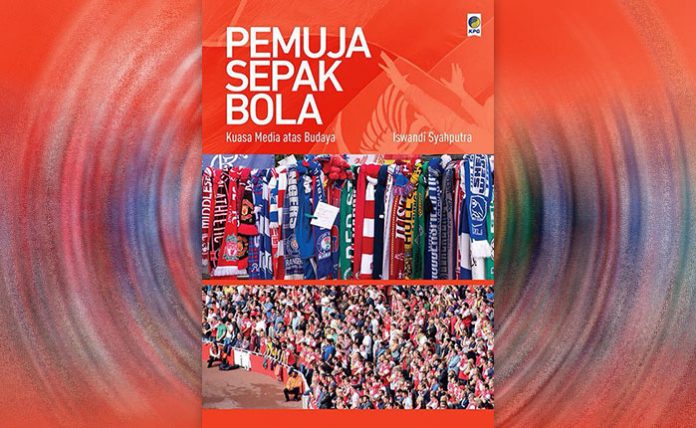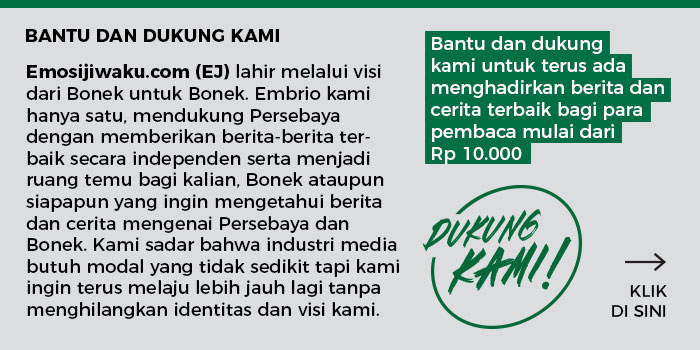Apa yang diingat orang ketika kesebelasan Liverpool bertemu AC Milan di partai puncak final Liga Champions tahun 2005 di Istanbul, Turki? Bagi pendukung Liverpool, apa yang terjadi saat itu adalah “keajaiban Istanbul”. Namun bagi pendukung AC Milan yang terjadi di Istanbul adalah sebuah bencana. Bagaimana mungkin dengan kedudukan 3-0 bagi kemenangan AC Milan justru Piala Champions singgah ke Liverpool?
Tim dan pendukung AC Milan telah berharap kemenangan manis. Hingga paruh babak kedua, Liverpool belum bisa mengejar skor. Masih 3-0 untuk AC Milan. Di situlah justru titik puncaknya. Satu persatu gol dilesakkan Liverpool. Skor menjadi seri dan dilanjutkan ke drama adu penalti. Rupanya keajaiban tetap berpihak ke Liverpool. Gerrard dkk akhirnya membawa pulang piala Champions. Pertandingan ini akan selalu dikenang oleh Liverpool dan pendukungnya sebagai mujizat sepanjang masa.
Apakah keajaiban berhenti di tahun 2005? Tidak. Liverpool secara “ajaib” dipertemukan kembali di tahun 2007. Juga pada puncak final Liga Champions. Yang membedakan adalah tempat berlaganya, yaitu di Athena, Yunani. Sejarah mencatat, Liverpool gencar mengancam gawang Milan dengan 12 kali tembakan. Bandingkan dengan Milan yang hanya 5 kali tembakan. Namun, keajaiban dewa-dewa Yunani berpihak pada AC Milan. Di akhir pertandingan, giliran mereka yang membawa pulang lambang supremasi sepak bola Eropa tanpa harus melalui drama adu penalti.
Tentu, bagi fans teriakan yel-yel, chant, sorakan kemenangan maupun kesedihan, air mata, dan tak jarang pula darah mengiringi setiap pertandingan. Apa yang bisa dideskripsikan dari olahraga ini?
Identitas dan Religiusitas
Iswandi Syahputra, penulis buku ini, mendeskripsikan sepak bola sebagai olahraga yang penuh dengan altar pemujaan. Pemujaan pada klub maupun kepada pemain. Simbol-simbol yang disematkan kepada klub maupun pemain tersebutlah yang mampu menghidupkan tidak saja olahraga itu sendiri namun juga industri secara keseluruhan.
Sebagaimana konsep imperialisme kuno yang menerapkan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel, sepak bola ini juga menerapkan 3G juga, yaitu Gold, Glory, dan Goal. Prinsip yang ke-3 yaitu goal inilah yang membentuk apa yang dinamakan sebagai “kegembiraan sosial”. Kegembiraan sosial ini yang membentuk kecintaan fans pada klub yang dibelanya. Jumlah gol kemenangan diasosiasikan dengan kejayaan (glory). Sementara bagi klub mendatangkan sponsor (gold).
Begitulah sepak bola. Olah raga yang menurut Franklin Poer (2006), sebagaimana yang dikutip dalam buku ini, telah menjadi produk globalisasi. Sepak bola merupakan cerminan kekuatan global, kekuatan politik, dan bahkan kekuatan budaya. Iswandi menuliskan bahwa identitas bukan hanya milik klub. Perseorangan hingga negara merasa berkepentingan dengan sepak bola. Proses identifikasi diri, sosial, dan kebudayaannya sama. Mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar di luar dirinya (hlm. 2).
Dalam sepak bola, ada individu-individu yang awalnya tak saling mengenal namun karena menjadi sesama pemuja sepak bola membuat mereka serasa terikat satu sama lain. Proses mengidentifikasi diri yang melahirkan konsep identitas inilah yang semakin menyemarakkan suasana di luar lapangan hijau. Fans club menjadi penanda untuk memuja klub yang sama dan tak jarang muncul pula fans garis keras yang di beberapa negara. Identitas kemudian menjadi begitu penting manakala klub yang dipujanya bertanding dengan lawan bebuyutan atau yang sering dinamakan sebagai duel klasik.
Sejarah juga pernah mencatat, bahwa peristiwa-peristiwa penting dalam sepak bola menumbuhkan pemuja fanatik yang di satu sisi dihindari namun di sisi lain rupanya berdampak pada pendapatan klub. Ada yang menarik dalam tulisan Iswandi terkait hal ini. Merujuk pada klub Glasgow Celtics yang merepresentasikan agama Katolik dan Glasgow Rangers yang merepresentasikan agama Kristen Protestan, fanatisme dalam sistem religi pun bercampur aduk dalam urusan bola. Saking ketatnya persaingan tersebut, pemujanya hanya menyebut nama belakangnya saja, Celtics dan Rangers.
Kapitalisasi dan Ilusi
Religiusitas dalam sepak bola (seperti halnya rujukan Liga Skotlandia di atas) kemudian berubah muka menjadi histeria massa yang disebarkan melalui media massa, utamanya dalam jaringan industri televisi (hlm. 92). Maka di sinilah peran media massa dalam menyebarkan pesan religi ini meski menjadi ambigu. Ada dua kepentingan bertarung wacana di sini. Di pihak pelaku (pemain dan fans) religiusitas dalam sepak bola menjadi pembebasan yang menghantarkan pada kegembiraan dan kebahagiaan kolektif. Sedangkan di pihak lain, religiusitas itu mengantarkan pada sistem kapitalisme global. Puncak dari kapitalisme global tersebut adalah piala dunia maupun Liga Champions. Iswandi secara bernas menjelaskan bahwa oleh karena religiusitas inilah maka sepak bola mampu mendeskripsikan kehidupan manusia yang mendambakan perdamaian dan kebahagiaan bersama.
Buku ini secara jelas dan komprehensif mampu menggambarkan mengenai bagaimana sepak bola bukan hanya perkara sebagai olah raga permainan. Olah raga ini memberikan semacam ilusi mengenai bagaimana objek beroperasi dalam tataran wacana budaya. Begitu pula individu serasa menjadi bagian penting dalam sepak bola oleh karena konsep-konsep sepak bola yang dideskripsikan oleh Iswandi dalam buku ini. Mulai dari bagaimana pembentukan identitas yang menjalar pada sistem fashion, agama, politik, maupun sejarah komoditas sepak bola itu sendiri.
Industri yang konon menghadirkan pragmatisme dalam objek keseharian telah mampu menjadikan sepak bola berikut fans-nya sebagai wilayah jual-beli. Arjun Appadurai (1988) maupun Igor Kopytoff (1986) dalam kaitannya dengan sepak bola ini telah menempatkan olah raga ini sebagai objek yang dinikmati setiap hari, entah bagi mereka sebagai pemuja maupun yang bukan; oleh mereka yang fanatik maupun yang bukan. Meski begitu, sepak bola tetap membutuhkan nilai perlawanan maupun menunjukkan sikap oposisi pada pemikiran industri. Syukurlah, di era komoditisasi ini, masih ada sikap fans yang realistis dan tidak mau terjebak pada ilusinya sepak bola. Di antara yang sedikit ini sebutlah The Kop-nya Liverpool. Mereka berani memprotes harga tiket yang ditetapkan. Begitu pula Bonek-nya Persebaya yang menolak jika ada pihak sponsor yang justru menjerumuskan klub kebanggaannya tersebut apalagi menjauhkan hubungan klub dengan pendukungnya. (*)
*Dosen DKV UK Petra Surabaya
Judul Buku: Pemuja Sepak Bola; Kuasa Media atas Budaya
Penulis: Iswandi Syahputra
Penerbit: KPG
Cetakan: Juni 2016
Tebal: xviii + 183 halaman