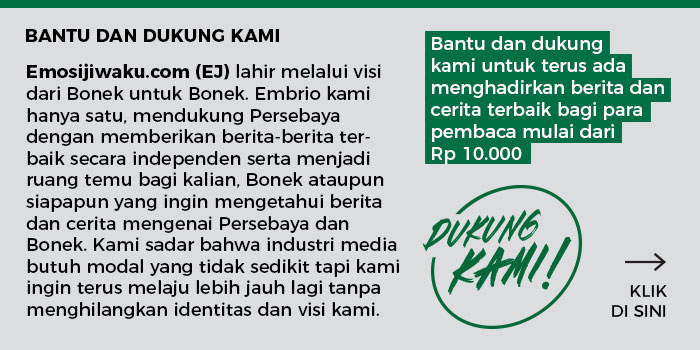Persebaya Surabaya kebanggaanku selalu, dimanapun kau berlaga kami selalu mendukungmu. Persebaya Surabaya mari bersama kita berjuang meraih mimpi kita semua jadi juara Indonesia.
— Chant for Persebaya
Riuh sorakan semangat terdengar hampir di setiap menit laga. Beribu-ribu pendukung Persebaya yang menamakan dirinya Bonek (Bondo dan Nekat) bersama memberi implus lewat lagu-lagu untuk tim kesayangannya.
Laga telah berhasil diselesaikan, misi menjadi champion sudah mampu dilaksanakan, hidangan berbuka puasa gelar habis dilahap dengan penuh kepuasan. Ya, tim yang berjuluk ‘Bajol Ijo’ dan ‘Green Force’ tersebut baru saja mengangkat trofi Dirgantara Cup di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Selama turnamen, skuad pimpinan Jendral Mat Halil dinilai sudah cukup memberi penampilan ciamik nan menarik pun pasti asyik.
Tidak hanya para pemain yang merasakan indahnya kemenangan, para suporter atas nama Bonek bersama suporter lain yang turut memberi partisipasinya juga tidak bisa dikesampingkan. Adagium ‘tanpa Bonek, Persebaya tak ubahnya tim yang biasa-biasa saja’ tampaknya bisa dibuktikan kebenarannya. Terlebih bagi yang menyaksikan langsung pertandingan sejak 27 Februari hingga 8 Maret 2017 itu, pasti menemukan fenomena dahsyat loyalitas tanpa batas suporter Persebaya.
Sebanyak 3.000-an Bonek datang berbondong-bondong dari berbagai penjuru daerah, mulai Surabaya sebagai basis sampai Jabodetabek sana. Mereka hadir dari berbagai kategori pendidikan maupun pekerjaan, dari pelajar sampai tukang antar, dari mahasiswa sampai pemilik usaha;,dari santri sampai angkatan dan polisi. Tak ada sekat di antara mereka, kaya dan miskin tidak ada gunanya untuk Bonek dan Bonita.
Apa yang melatari loyalitas, totalitas, dan kenekatan tak terbatas demikian? Tampaknya untuk menjawab itu, penulis harus meminjam istilah ‘imagined community’ dari Bennedict Anderson, suatu istilah yang membuat Oryza Ardyansah W (2015) memberi judul bukunya “Imagined Persebaya”.
Sama halnya dengan keberadaan tim-tim lain, Persebaya awal (SIVB dan Persibaja) merupakan kesatuan pemain, pelatih, manajemen, dan official tim belaka. Akan tetapi tidak sesederhana itu, Persebaya di kemudian hari menjelma menjadi suatu ikatan identitas sosial, tempat para penduduk Surabaya mendapat eksistensi dan kepuasan diri. Bagi masyarakat Surabaya, Persebaya adalah salah satu maskot luhur yang harus hidup dan dibela serta diberi dukungan motorik. Anggapan itu tidak terlepas dari karakter ‘jogo rego awak dewe’ (menjaga harga diri kita) yang sudah mengakar lama di masyarakat Brantas-an, khususnya Surabaya. Oleh karenanya, Persebaya tak ubah komunitas sosial-budaya yang diimajinasikan para pendukungnya. Sama halnya dengan keberadaan Bangsa, Persebaya lahir dan hidup dari imajinasi-imajinasi sebuah kejayaan oleh para pendukung yang ternyata keluar dari basis teritorial, mencakup semua daerah di Indonesia bahkan beberapa negara tetangga.
Ya, pendukung yang menyerahkan cintanya pada Persebaya tidak hanya dari Surabaya saja. Bonek telah merambah dan membuat virus verstehen -meminjam istilah Weber tentang rasa kepemilikan- menyebar ke penjuru sana. Tidak heran jika lantas muncul komunitas pendukung yang memakai nama semisal Bonek Jogja, Bonek Jabodetabek, Bonek Pasuruan, Bonek Jember, Bonek Rembang, Bonek Borneo, bahkan Bonek Malaysia dan Bonek Swiss.
Secara rasional, manajemen komunitas yang tidak dikelola secara baik lewat adanya sosok ketua atau sejenisnya akan menimbulkan anarki atau disorder. Akan tetapi secara praktiknya, Bonek yang sudah terkenal tidak mengenal istilah ‘ketua’ justru berkata sebaliknya. Tengoklah peristiwa Gruduk Jakarta dan Gruduk Bandung, saat aparat keamanan mengakui ketidakberdayaan untuk membendung arus aspiratif tersebut. Alasannya sederhana, yakni Bonek tidak ada kepala komunitasnya, selain juga tekad perjuangan yang sudah mengkristal. Adapun keberadaan misal Andie Peci hanya sebagai juru bicara dan tetua (bukan senior, istilah yang dimanfaatkan untuk mengakumulasi kekuasaan perorangan dalam organisasi).
Kultur baik demikian tidak selalu berjalan mulus sebagaimana cita-cita dalam pandangan moral. Bonek sering kali diberitakan oleh media mainstream sebagai perusak, perusuh, dan pembawa kegaduhan. Dalam hal ini, penulis tidak perlu memberi bukti yang membusa, cukup dengan pembaca membandingkan dan merasakan langsung antara realita seduluran (persaudaraan) dengan teks berita yang memojokkan. Simak saja saat beberapa Bonek terlibat kerusuhan, pasti semia berita menuliskan dengan nada sinis, intinya ‘Bonek Terlibat Tawuran’. Tetapi pernahkan berita mainstream mengeksplor dan menegaskan kontribusi Bonek saat melakukan penggalangan dana untuk Korban Aceh, Banjir Garut, Banjir Jakarya, Gempa Banjarnegara, Bangun rumah bagi keluarga yang tidak mampu di Trenggalek, dan masih banyak lainnya.
Maksud penulis demikian bukanlah untuk menafikan kebiasaan yang memang harus diakui merupakan kekurangan Bonek, seperti ikhwal tiket, melainkan memberi suatu perspektif baru dalam membaca sebuah kedirian komunitas. Terasa tidak ada prinsip al-‘adalah dalam pemberitaan selama ini, nihil kode etik faktual dan akuntabel di berbagai informasi, nir–tabayyun saat membahas tentang suporter tim yang syarat akan prestasi. Hal terakhir yang penulis sebutkan tadi, yakni tabayyun atau klarifikasi, merupakan poin paling esensial yang seyogyanya membuat media mainstream tidak begitu saja memberi justifikasi atas perilaku Bonek, pun suporter lainnya.
Mengingat keberadaan media dalam nalar demokrasi sebagai pendidikan opini berikut perspektif publik, maka ‘mencari kebenaran di balik kejadian’ secara demonstratif sangatlah urgen. Misalkan saja, pelintiran akronim Bonek menjadi hanya ‘Bondo Nekat’ tanpa penghubung ‘dan’ di tengahnya sudah menciderai dan membelokkan fakta sejarah pada masyarakat (simak video Alm. Supangat di media youtube). Akhirnya, Bonek diidentikkan sebagai suporter yang sering mengawal timnya dengan hanya berbekal ketekadan tanpa memiliki modal perjalanan dan makan. Lalu kemudian muncullah stereotip ‘Bonek sang Penjarah’ warung makan dan toko klontongan.
Kritik yang lain, misal, sedari awal pelaksanaan Dirgantara Cup, hal yang dipampang dan ditekankan oleh media mainstream berintikan ‘Bonek dimohon tidak rusuh’. Sekilas hal itu tampak seperti himbauan, padahal di dalamnya terdapat stigma yang tanpa disadari menimbulkan kegaduhan. Praktis di beberapa sosial media, selama Bonek berada di Jogja, rating pembahasan Bonek oleh masyarakat tertuju pada berbagai pelaporan yang negatif. Di satu sisi, itu memang bagus sebagai kontrol sosial. Akan tetapi di sisi lain, hal demikian berarti mengaburkan fakta lain dari Bonek yang jauh lebih banyak sisi positifnya.
Sederhana saja, adakah suporter sebanyak Bonek yang merelakan dirinya tidur di stadion tim lain hanya untuk memberi doa dan dukungan langsung untuk tim kebanggaannya? Bukankah suatu kebaikan seperti para gerombolan Bonek yang saling berbagi rizki materi dan kopi bagi sesamanya? Apakah semua media mainstream lupa bahwa Bonek telah menegaskan tradisi luhur Indonesia untuk saling ‘nulungi’, gotong-royong, kerjasama, ‘joinan’, pantang putus asa, dan pantang menyerah terhadap urusan dompet?
Pertanyaan reflektif di atas tampaknya harus segera dijawab oleh para pembaca, khususnya yang gagap dan ‘kagetan’ terhadap media tanpa melakukan pelacakan secara masif. Selain sebagai bentuk kritik terhadap diri, juga bisa menjadi barometer kecerdasan sebagai pembaca. Akhirnya, mari berbondong-bondong berani untuk mendeklarasikan perbaikan diri. Dan tak kalah penting adalah ayo bangsa Indonesia berbangga pada tim asli dari rahim Bumi Pertiwi. Salam Satu Nyali, Wani.
… Sejarah sepakbola adalah sejarah Persebaya. Pun demikian, Bonek juga sejarah penting dalam sejarah perkembangan sepakbola di Indonesia. (Fajar Junaedi, 2015)
*) Ferhadz Ammar Muhammad, Kalijaga Class Bonek Jogja