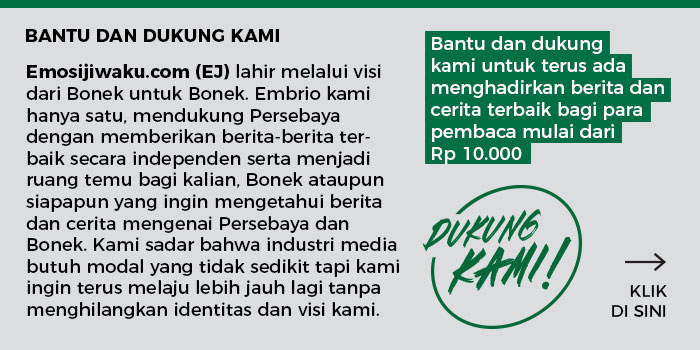Di era Perserikatan, sepak bola merupakan simbol dan identitas daerah seutuhnya. Seluruh pemain mayoritas hasil pembinaan internal mereka, bermain dan pensiun sebagai abdi negara menjadi PNS daerah dan lain-lain. Era itu tidak ditemukan transfer antar klub dengan nilai rupiah yang fantastis. Pemain akan bermain hingga pensiun di mana dia mulai bermain. Maka, di masa itu pula sangat mudah di dapatkan “one man one club” seperti almarhum Choirul Huda.
Sepak bola profesional menggeliat mengikuti perkembangan. Setiap pemain dapat menentukan masa depan dari berbagai macam klub. Tak ada lagi primordial di sana, tak ada lagi sifat kedaerahan mendominasi. Yang ada justru kebutuhan tim untuk terus berprestasi sepenuhnya.
Persebaya, mantan klub perserikatan yang telah meleburkan diri sebagai klub profesional seutuhnya. Membina usia dini hingga kompetisi internal, menjadikan klub ini sebagai “pabrik” pemain nasional dan berbakat.
Musim kompetisi 2018 yang kembali di ikuti persebaya banyak menuai ragam kritik, seiring dengan gelombang eksodus mantan pemain Persipura ke Persebaya. Hampir setiap lini Persebaya ada pemain asal klub yang telah empat kali juara Liga Indonesia itu. Kritikan paling satir adalah “Persebaya rasa Papua” dan “Persebaya Jayapura”.
Hadirnya Isaac Wanggai menambah kelengkapan kritikan itu. Belum reda ingatan Bonek akan Andik Vermansah, manajemen menambah “bahan” oposan Persebaya untuk luwes menggempur Persebaya dengan kritikan. Hal ini sangatlah wajar, jika kedaerahan dan primordial menjadi acuan dan panduan membangun tim.
Persebaya masihlah tetap tim terbaik dalam membina pemain lokal, baik dari internal maupun non internal. Persebaya adalah tim profesional rasa konvensional yang percaya segenap hati pada pemain binaan.
Sebulan dua bulan ke depan, carilah tim peserta Liga 1 yang memasang starting eleven dengan 3-4 pemain binaan internal/akademi mereka. Sudah dapat dipastikan, itu hanya bisa dilakukan Persebaya Surabaya.
Masih percayakah Persebaya rasa Papua?