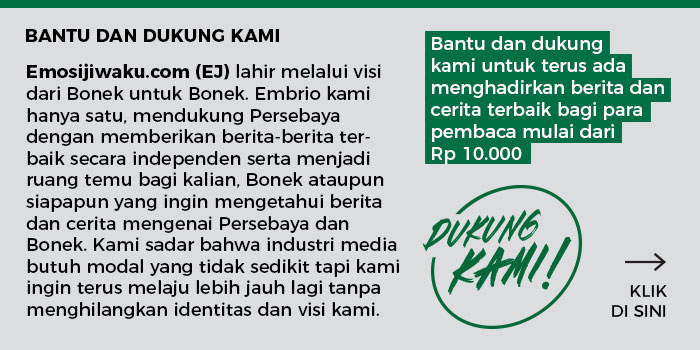Catatan ini bersumber dari ‘sengaja dengar’ saya di waktu dini hari yang dingin, 21 Mei 2018 yang lalu. Itu semua diawali dari ketidaksengajaan saat saya melihat dua suporter duduk lesehan di depan warung ‘2728’ –salah satu warkop di sudut jalan Ngagel. Satu orang berbaju hijau dengan nama punggung bertuliskan ‘Dio’ terlihat lebih banyak melempar cerita dan humor. Sedangkan temannya yang berbaju merah –kalau tidak salah membawa kaos bertuliskan ‘Rizky’– cenderung banyak bertanya dan cekikikan. Hangat sekali suasana pukul 01.00 WIB itu. Saya yang sedari tadi di situ, diseret oleh keinginan untuk semakin dekat. Ya meski gak bisa gabung, paling tidak bisa mendengar bahan obrolan mereka. Saya putuskan mengambil posisi nyaman di bawah temaram lampu, tepat sebelah warung kopi – dua meter dari mereka.
“Riz, tanggal 3 Juni, Persija lawan Persebaya lho. Kite bisa setribun, tidak?” Dio bertanya, sederhana.
“kagak tahu gue, cak. Katanya sih di Jogja, kan lu tahu sendiri kandang tim gue masih dilempar sono-sini.” Rizky menimpali. Dilihat dari mimik wajahnya, Rizky ini agak marah, terutama di diksi ‘lempar sono-sini’.
“Iya, riz. Kagak perlu sedih gitu, lur, petarung yang hebat dan meyakini jalan kebenarannya pandai menguasai berbagai medan tempur. Kan lu tahu teorinya Robert Greene: “Menempati Medan Moral yang Tinggi”. Ngomong-ngomong, kalau memang di Jogja dan laga berlangsung tanggal 3 Juni, maka ini momentum baik bagi sepak bola Indonesia.” Dio mulai nerocos.
“Menarik. Teruskan penjelasanmu, dulur.” Rizky mulai keranjingan cerita.
“Jika media transmisi antar manusia adalah akal dan hati, setidaknya ada tiga hikmah dan nasehat luhur yang tersampaikan. Pertama, sejarah kota kita –Jakarta dan Surabaya– telah memaksa suporter sepak bolanya menjalin kerja sama. Di masa kolonial, Surabaya relatif lebih digandrungi tokoh pergerakan untuk menjalin konsolidasi dan kerja sama perjuangan. Puncaknya di tahun 1945, saat Surabaya menjadi satu-satunya kota yang berhasil memberi perlawanan berarti untuk tiga negara komparador: Jepang, Belanda, dan Inggris (Frank Palmos, 2016). Kondisi yang hampir sama dialami Jakarta. Ia sudah lama menjadi pusat segala kebijakan negara lahir. Meski demikian, jangan lupakan Jogja.
Aku pikir kamu masih ingat sejarah berdirinya PSSI, kan? Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi saksi sejarah tempat dicetuskannya induk sepak bola nasional kita. Namun perlu dicatat, sebelum Jogja dipilih untuk rapat pendirian PSSI, Jakarta dan Surabaya sempat menjadi pilihan –sebelumnya juga sudah ada IVB (Indonesische Voetbal Bond) yang lahir di Surabaya. Sayangnya, karena pertimbangan waktu dan ongkos, maka Jogja menjadi pilihan yang tepat –setidaknya itu yang disampaikan Wakil Jakarta dulu (Panditfootball). Lha, dari sedikit cerita itu bisa dikatakan, sekali lagi bro entah ini ketepatan nasib atau memang sudah ada invisible hand dari Tuhan, kita bisa mengatakan, bahwa sejak dulu Surabaya terkenal menjadi pusat dialektika pergerakan, sedang Jakarta sampai kini dengan statusnya sebagai ibu kota tentu menjadi sentrum kebijakan skala nasional, dan Jogja selalu menjadi saksi romantis sejarah yang melibatkan keduanya. Kebetulan? Entahlah.” Panjang sekali Dio menjelaskan.
“Hahaha… bentar sob, sebelum lu lanjutkan ke poin kedua dan ketiga, ngomong-ngomong sejarah gue jadi ingat rivalitas tim nih. Menurut gue, rivalitas sepak bola Indonesia yang berisi persaingan sejarah, nama, dan piala, tentunya mencantumkan nama Persija vs Persebaya sih. Ini mirip sekali dengan rivalitas Manchester United vs Liverpool, konflik pelabuhan. Perebutan nama besar di linimasa sejarah sepak bola Ratu Elizabeth, ditambah penggulingan atas dominasi satu sama lain mampu menyita perhatian seluruh pecinta sepak bola dunia. Guyonnya, dalam konteks Indonesia, Tanjung Perak vs Tanjung Priok. Hahaha. Bedanya, disebabkan pendiri PSSI, salah duanya ada VIJ dan SIVB (nama Persija dan Persebaya doeloe), membangun atmosfer sepak bola sebagai alat pemersatu dan bambu runcing pergerakan, maka rivalitas kita musti cerdas, bukan? Dan di sini, Persija unggul selisih sedikit piala di atas Persebaya. Semangat ya. Hehe.” hebat sekali Rizky mengkorelasikan sepak bola beda negara itu.
“Hahaha, siap. Aku lanjutkan ke poin kedua. Sebenarnya poin kedua ini masih bersangkutan dengan yang pertama. Jika tadi kita sudah berbicara sejarah yang mengharuskan hubungan Jakarta dan Surabaya ini terjalin erat, maka sekarang kita berbicara tentang laga 03 Juni sebagai momentum dan langkah kritis membedah kekerasan stigmatik dari kata ‘rivalitas’. Jika dulu kita mendengar Bonek-Viking vs The Jak-Aremania, maka sekarang musti ada pertanyaan: benarkah Bonek dan The Jak bersitegang? Jangan-jangan itu hanya bualan atau lontar masa lalu yang tak mencerdaskan? Lihat saja saat ini, kamu dan aku duduk dan ngopi bareng; kamu The Jak dan aku Bonek. Mengapa kita nyambung? Aku benar-benar khawatir jika sebenarnya ini adalah setting dari pihak tertentu dalam scale shift atau bisa disebut eskalasi, yakni setting permasalahan yang ada agar menjadi besar dan meluas hingga melibatkan aktor-aktor dari berbagai kelompok yang lebih banyak (Van Klinken, 2007). Bisa dianalogikan, kamu karo aku ini tidak ada masalah apa-apa, tapi berhubung kamu punya temen yang lagi berantem sama aku, akhirnya kamu dipaksa harus turut memusuhi aku. Konyol, bukan?
Pertanyaanku tersebut lahir karena tidak rela jika rivalitas suporter seperti anak TK: yang berantem hanya gara-gara tidak kebagian kelompok bermain, padahal dia sendiri yang telat masuk ke barisan; yang mencari teman berbadan besar agar bisa menghalau teman belakang yang lebih kekar. Pokoke aku gak pengen kalau kita kayak suporter Feyenord yang dihajar oleh gabungan suporter Nancy-Strasbourg. Bukan karena kita takut, tetapi ini demi merawat kritisisme dan akal sehat. Dan aku harap, suasana warung kopi ‘2728’ yang damai ini bisa menjadi kabar untuk keluarga besar kita dan Indonesia.
Aku langsung ke poin ketiga deh ya, biar cepet, udah malam, yakni kritik buat aparat pengaman. Kenapa tak bilang demikian? Secara kon kan pasti tahu bagaimana logika panpel dan aparat sekarang. Mereka tidak paham dunia suporter, tapi berlagak paling solutif, dan celakanya, tindakan mereka kadang represif. Alih-alih mengamankan, justru menebalkan rivalitas yang sudah kita pertipis. Kamu sudah pernah dengar cerita 03 Juni 2012 yang terkenal dengan sebutan “Arogansi Aparat Tiga Juni (Arapagani)” itu?” Dio mulai serius dan meninggikan suaranya.
“Saat Persebaya menjamu Persija di Tambaksari, bukan? Laga yang gegara tembakan gas air mata aparat menyebabkan satu Bonek tewas. Kalau itu, gue tahu sedikit sih dari penuturan saudara. Kenapa emang?” Dilihat dari gayanya, Rizky ini orangnya haus rasa ingin tahu.
“Ya, tepat. Kalau yang aku baca dari tulisan Oryza A. Wirawan, ternyata tanggal dilangsungkannya laga enam tahun lalu yang memakan korban itu sama dengan laga yang akan kita hadapi besok – 3 Juni. Entah ini kebetulan atau tidak, nyatanya memang sepak bola selalu membawa metafisika di dalamnya, seperti kata Ammar Mildandaru (2014). Aku meyakini ada narasi besar dari Tuhan. Oke kalau kebanyakan dari kita tidak percaya dengan hal yang metafisik di sepak bola, tetapi bahwa segala unsur terkait giringan bola bisa memberi hikmah dan pelajaran, itu musti kita sadari. Seperti kecocokan tanggal ini. Jika boleh menerka narasi Tuhan, tampaknya Dia hendak berkata: innallaha la yuhibbul mu’tadin –Dia tidak suka orang yang melebihi batas. Dengan demikian, maka segala tindakan melebihi batas apalagi represifitas terhadap suporter tidak dibenarkan, kecuali dalam kondisi mencekam, itu pun ada ketentuannya dengan tetap mengindahkan Hak Asasi Manusia.
Tampaknya dalam dunia suporter, aparat musti belajar dari Pak Coki Manurung, Kapolres Kota Surabaya dulu. Pak Coki ini lebih mengedepankan langkah preventif, common sense banget lah, mulai dari silaturrahim ke komunitas-komunitas Bonek, sampai turut berbagi takjil di bulan Ramadhan.” Jelas Dio.
“Gue setuju sama penuturan lu, sob. Sebenarnya dari tadi gue diam karena sepanjang penjelasanmu, terngiang satu kata dari salah satu legenda sepak bola ternama, Sir Alex Ferguson. Dalam buku biografinya, ia menulis tentang tantangan dunia sepak bola begini: banyak kali tantangan itu disebabkan oleh kerapuhan manusia, serta emosi dalam pertandingan bisa menjebak kita. Dan saya merasa, kata-katanya sedang mencari ruang pembuktian, sekarang.” Tandas Rizky dengan merunduk.
Suasana tiba-tiba hening. Tak ada obrolan dan guyonan setelah itu. Hawa dingin yang sedari tadi ikut menghabiskan kopi di meja itu semakin kencang bernafas, memaksa kedua sahabat yang sedang akrab-akrabnya musti berpindah tempat, segera. Saya yang dari tadi mlongo saja pun sudah merasakan ketidaknyamanan tempat itu, terutama saat Truk melintas di depan kami tanpa aba-aba. Hampir saja moncongnya nyasar ke motor Dio. Sembari memasukkan buku catatan, saya masih mendengar mereka berdua bercengkerama dengan mbak kasir. Namun saat saya menoleh ke arah suara, mereka sudah tak ada, berlalu entah kemana.