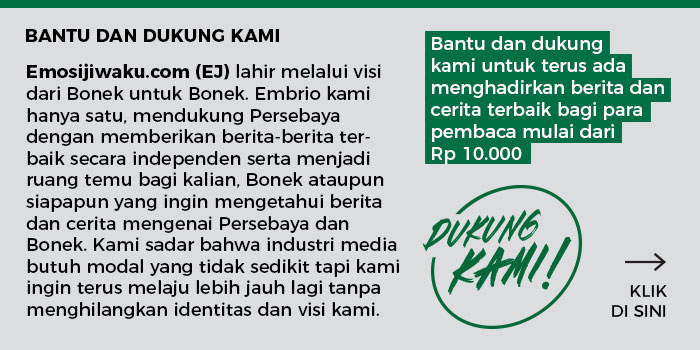Mendiang Bapak mengenalkanku pada sosok pesepak bola bernama sama dengannya, Syamsul Arifin. Kami anak-anaknya masih kecil-kecil saat itu. Saat kami “melihat” Persebaya dari radio kecil di jaman Orde Baru. Jaman yang katanya semua murah bisa dibeli, nyatanya harta kami hanya radio, pengen nonton tv ya ke Balai Desa. Mungkin dari situlah, kecintaan Bapak pada Persebaya ditularkan.
Kira-kira tahun 1990 saat diajak mengantarkan teman yang ikut Kejurnas catur yunior di kampus Stiesia, itulah kali pertama saya menginjakkan kaki di Surabaya. Visual yang membekas adalah di mana-mana berkibar bendera hijau. Dari dalam bemo yang kami tumpangi warna hijau benar-benar mendominasi kota. Tahun yang sebenarnya di jaman Orde Baru “kuningisasi” harus dilakukan. Tembok, jembatan, genteng, pohon, dan lain-lain harus dicat kuning, alasannya biar terang. Tapi itu alasannya Orde Baru. Di Surabaya saat itu justru bukan warna kuning, tetapi hijau. Saya belum mengenal “perlawanan” saat itu.
Kemarin, saya menjadi tahu mengapa kota ini begitu hijau. Otak yang merekam kejadian-kejadian kecil maupun yang saya alami segera saja mengalirkan hasrat mencatatkannya. Sudah dua tahun terakhir ini saya meneliti tentang Bonek dalam sudut pandang seni visualnya, hasilnya masih satu artikel ilmiah yang sudah dipresentasikan tahun kemarin. Dari dunia visual Bonek itulah makin menajamkan saya tentang teks dan konteks. Nah, kemarin adalah saat mencari konteks itu. Ditemani pak Deddi Dutoo, yang fansnya PSIS, dan Maket Melekatt yang arek Suroboyo asli, kami berangkat ke Stadion Bung Tomo.
Menyingkirkan dulu penilaian moralis yang positivistik tentang Bonek yang tidak berhelm, Bonek yang susah diatur, Bonek yang kasar, maupun cap pada Bonek yang bla bla bla lainnya. Memori justru merekam tentang bagaimana “paseduluran” bahkan ke yang tak kenal, sikap “mundhuk-mundhuk” ke yang lebih tua, doa mereka dan sikap solidaritasnya mau membukakan jalan saat kami ikut membantu mengevakuasi seorang Bonita, Bonek wanita, yang pingsan saat bubar pertandingan. Kata-kata yang lucu yang keluar begitu saja saat kemacetan luar biasa terjadi, mereka yang menjaga dan memberi cahaya lampu dari HP-nya pada seonggok batu dan potongan pohon demi Bonek lainnya tak tersandung dan jatuh.
Tentang antrian Bonek yang dehidrasi di warung saat membeli air minum, tentang mereka yang membeli es batu saat air minum di warung habis hingga akhirnya memecah es batu buat diklamuti kayak permen, tentang tak saya dapati gesekan ala konser dangdut yang berujung ricuh padahal ada 55.000 orang tumplek blek, tentang Dahlan Iskan, jendral, menteri, atau pemegang tiket VIP yang ikut jalan kaki 5 km menuju stadion begitu juga saat arah pulang, tentang sesepuh dan wartawan bola legendaris yang juga ikut jalan kaki, tentang mereka yang membantu menggendong anak kecil yang kecapekan, maupun tentang bagaimana mereka melindungi dan menghormati wanita dan juga kepada orang tua yang membawa anak kecil.
Ya, mereka tetap bukan malaikat, identitas mereka di visualitas apapun yang dibuat dan diciptakan masih menunjukkan mereka ada di bumi. Dalam kaca mata positivistik, mereka belum keren. Namun minimal saya jadi memahami.
Benarlah kata teman saya, cobalah sehari saja menjadi Bonek untuk merasakan pegalnya kaki, dehidrasi, solidaritas, atau menempuh logika tak wajar. Jika berhasil melampauinya, bagus! Tapi kalo tidak, bejat utekmu!