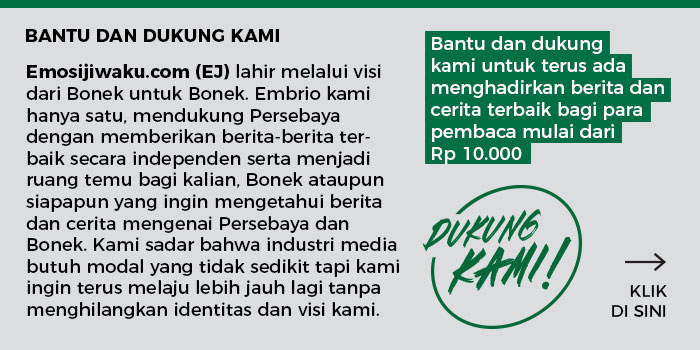Sekarang adalah masa pembangunan. Maka untuk usaha ke depan, marilah kita menengok masa yang telah lalu. Mana-mana hal yang salah pada masa lalu, marilah kita buang jauh-jauh; mana-mana hal yang kurang, marilah sekarang kita sempurnakan, dan mana-mana yang baik, marilah sekarang kita tambahi. (KH. A. Wahid Hasyim, 1944)
Paska kembalinya Persebaya dari setrapan mafia sepak bola, klub yang bermarkas di Surabaya itu melakukan berbagai renovasi. Mulai dari kepemilikan klub hingga perilaku suporter pun tak lepas dari mata perbaikan. Hal yang dirombak dan sempat santer dibicarakan salah satunya adalah pengisi kursi pelatih. Hingga akhirnya Iwan Setiawan–pelatih yang bagi penulis mirip Jose Mourinho itu, baik mulut maupun taktik–diminta duduk di kursi.
Perbaikan di segala lini memberi konsekuensi logis pada pembangunan citra diri (Self Branding). Jika kebanyakan klub–yang belum pernah separah Persebaya dalam hal kevakuman–terfokus pada teknis yang hanya tampak di residu, maka Persebaya melakukan hal yang lebih dari kegiatan itu–setidaknya lebih disoroti oleh berbagai pihak. Adalah rasisme–penyakit yang dengan gigih dijadikan common enemy (musuh bersama) dalam dunia sepak bola–, problem yang menambah pekerjaan rumah Persebaya. Tidaklah berlebihan jikalau penulis mengatakan demikian, sebab hampir masih ditemui–jika kita jujur mengakui–kecenderungan masyarakat umum yang memberi lebel itu kepada ‘Tentara Hijau’ Bajul Ijo, yakni Bonek–meski kita semua tahu, bahwa sesuai analisa framing asumsi demikian tentulah tidak melulu benar, sebab kembali ke keinginan dari siapa yang memberitakan.
Itu pun kalau media sebagai penguasa otak masyarakat menginsyafinya. Bagi penulis, menanggapi asumsi demikian dengan cara mengklaim kebenaran dan menjustifikasi kesalahan–apalagi memberi apologi (pledoi: pembelaan) dengan mengkambinghitamkan salah satu pihak luar–tidaklah penting, sebab menurut kelakar penulis tentu lebih afdhal adu karya timbang adu mulut, bukan?. Oleh karena itu, daripada capek senam mulut yang tak mencerdaskan, mending berpikir yang produktif: mengapa harus rasisme yang diperangi?.
Setidaknya, menjawab pertanyaan di atas akan membuat kita mudah mengidentifikasi perilaku yang telah diperangi oleh dunia internasional itu. Secara lebih fokus, setidaknya, para pecinta sepak bola akan dengan mudah memahami, bahwa rasisme pun bisa diperbuat oleh berbagai komponen, termasuk pelatih, seperti yang ditunjukkan Iwan Setiawan saat berkomentar mengenai lawan: “Madiun Putra menerapkan permainan kampung” (Emosijiwaku.com, 18/04).
Bukan tanpa alasan penulis memberi justifikasi bahwa Iwan telah melakukan tindakan rasisme. Jikalau toh berbagai pihak yang fanatik ke Iwan membantah itu dengan memberi argumen atas nama demokrasi, maka pertanyaannya: apakah kebebasan berpendapat harus membesarkan diri dan mengecilkan badan lain? Bukankah dalam nalar Indonesia, etika dan moralitas menjadi panglima daripada sekedar membusungkan dada?. Praktek yang terjadi, sering kali klub–badan– yang merasa besar dan memiliki gelar bergelimang merasa lebih tinggi dan cenderung menginferiorkan klub yang diasumsikan berada di bawahnya. Implikasi lebih jauh, kerap kali kekerasan yang sebenarnya dan sejujurnya ditakutkan oleh pecinta sepak bola bermula dari ucapan rasis dalam berbagai bentuk, utamanya yang berasal dari mulut.
Rodolfo Stavenhagen (1996)–sebagaimana dikutip Muhaimin Iskandar– memberi deskripsi sederhana mengenai rasisme, yakni suatu keyakinan akan adanya superioritas dan inferioritas dari pergumulan ras yang mengarah pada ekspresi diskriminatif secara sistematis. Meski awalnya rasisme terpraktekkan dalam sektor genetik, ilmu pengetahuan, dan nasionalistik, tetapi seiring berjalannya waktu, rasisme pun bisa masuk menjadi berbagai manifestasi (wujud), termasuk fanatisme dalam sepak bola. Itu disebabkan karena hubungan yang dibangun dalam sebuah klub sepak bola sangat mengikat kuat hingga membentuk satu badan dan keyakinan. Sebagaimana rasisme memberikan ruang bagi munculnya kegagahan atas kelompok lain, pun demikian halnya yang terjadi di dunia kompetitif. Atas dasar keunggulan yang dimiliki dalam berbagai bidang kehidupan, kelompok superior seakan menjadi ‘guru’ yang harus dipatuhi. Praktek kepongahan itu mengindikasikan adanya akumulasi kekuasaan di satu pihak dengan penundukan atas pihak lain–mirip sebagaimana teori Edward Said (2010) menjelaskan mengenai Barat vis a vis Timur.
Apakah perkataan Iwan sedemikian beratnya hingga layak dikaji jeli dengan teori kekuasaan? Menurut penulis, apa yang dikatakan Iwan termasuk pelanggaran yang tanpa disadari membawa implikasi buruk bagi kesehatan kompetisi sepak bola. Meski demikian, pembaca tak perlu pusing berpikir bahwa ini persoalan gawat yang harus dicarikan obat yang dahsyat. Cukup dengan memperlebar spektrum #NoRasis ke ranah singgahsana kepelatihan. Bahwa #NoRasis tidak hanya diperuntukan dan dijejali untuk suporter belaka, melainkan semua pihak tanpa istisna’ (pengecualian).
Penulis insyaf, bahwa fitrah kompetisi sepak bola Indonesia yang mempertemukan berbagai olah bola nan asyik meniscayakan adanya kelompok yang kualitasnya jauh lebih ciamik. Keberadaan fakta yang demikian bersifat nature dan tidak politis-dalam artian tidak dianggap lebih berkuasa atau superior dari yang lain. Oleh karenanya bagi penulis–sebagaimana juga Wahid Hasyim–, hal itu tidak perlu dipertentangan secara egois–merasa layak memonopoli kemenangan. Justru penggunaan bahasa yang mengandung rasisme itu merupakan warisan kolonial yang sudah menyerang mentaliteit bangsa Indonesia. Bukankah kelahiran sepak bola Indonesia bertujuan untuk melawan itu? Jikalau iya, maka seyogyanya banner ‘Revolusi’ yang dulu pernah diangkat oleh Bonek, layak untuk ditampakkan ke depan Bang Iwan.
Akhirnya, Kepedulian suporter atau fans terhadap masalah sosial terkait dengan sepak bola masih tinggi. Terutama dalam menghapus dua masalah utama dalam sepak bola, yaitu rasisme dan kekerasan. (Anung Handoko, City of Tolerance, 2008)
*) Ferhadz Ammar Muhammad, Kalijaga Class Bonek Jogja