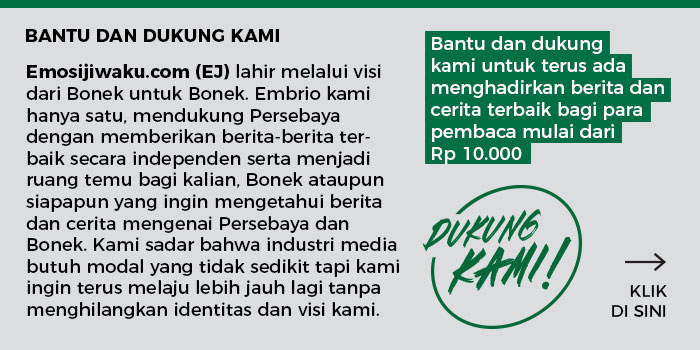Lagi, kita bisa memutuskan untuk mengganti diletantisme (suatu paham yang mencintai seni-seni murni sekadar untuk hiburan) yang tragis itu menjadi tindakan (action) dan dalam hal ini kehidupan manusia menjadi tandingan-tandingan di dalam suatu permainan. (Albert Camus, ”Pemberontak”.)
Awal Liga 2, kompetisi berjalan normal seperti biasa. Setiap grub fokus pada kemenangan agar bisa lolos ke babak 16 Besar meski harus melewati bara laga. Rata-rata laga yang membara itu dimotori oleh pertemuan dua tim klasik yang syarat dengan kejadian masa lalu, seperti Persebaya dengan PSIM, atau dendam yang belum usai, misal PSCS dengan PSS yang pada tahun 2016 dipertemukan dalam gelanggang perebutan Juara ISC B.
Iya, itulah awal perjalanan Liga 2. Tepat sebelum utak-atik pemilik invisible hand, tangan-tangan tak terlihat, memporak-porandakan kenormalan setiap laga. Baiklah, agar tidak terkesan pembahasan ini melebar, penulis akan memfokuskan diri untuk melihat sejauh mana keabnormalan ini menimpa Persebaya. Mungkin saja, apa yang dirasakan Persebaya tidak jauh berbeda dengan kegilaan di luar nalar sepak bola ‘Fair Play’ yang dialami hampir semua klub.
Pertama, mafia skor kembali unjuk gigi. Masih ingat saat Persebaya bertandang di Kalimantan Selatan untuk menghadapi Martapura FC? Terlihat jelas bukan, seorang pria di menit akhir laga memberi kode kepada hakim pertandingan? Terasa sekali bukan, kerugian Persebaya sebab molornya tambahan waktu menjadi malapetaka kalah 2-1?. Tampaknya, kemelut laga pada hari Minggu, 30 April 2017 itu, mengejawentahkan suatu kondisi realistis babak-belurnya persepakbolaan kita, hanya saja banyak mata yang tak bisa menyaksikannya: wasit sering kali bermain mata dengan mafia hingga menjahati laga, dan lisensi wasit acapkali digunakan untuk membungkam kritik dengan peluit, mirip seperti dawuh Emha Ainun Nadjib ‘Cak Nun’ dalam OPLes (Opini Plesetan), bahwa “Kejahatan adalah nafsu yang terdidik. Kepandaian, seringkali adalah kelicikan yang menyamar. Adapun kebodohan, acapkali, adalah kebaikan yang bernasib buruk. Kelalaian adalah i’tikad baik yang terlalu polos. Dan kelemahan adalah kemuliaan hati yang berlebihan.”
Kedua, sesat pikir dan jiwa mengalahkan esensi sepak bola. Ya, baru terjadi di Indonesia, kompetisi legal digelar tertutup dengan tanpa penonton atau pendukung kedua klub yang bertemu, padahal masing-masing klub tidak ada satu pun yang mendapat sanksi. Sungguh nyata di belantara sepak bola nasional, esensi sepak bola sebagai hiburan sekaligus ikatan kultural dipaksa hilang oleh persepsi–bukan asumsi, tetapi lebih seperti penderita penyakit Psikosis (gangguan jiwa)–yang tidak pernah terjadi, misal keputusan laga antara PSBI Blitar melawan Persebaya di Stadion Sultan Agung digelar tanpa penonton, sebab menurut saya –sekaligus menolak apologi perizinan–pihak penyelenggara khawatir dengan keamanan laga.
Kemudian, tampaknya penyakit Psikosis yang diderita oleh penyelenggara laga pun belum sembuh. Keputusan terakhir tentang status tanpa penonton laga Persinga Ngawi vs Persebaya menambah bukti penyakit itu. Anehnya, saat ditanya mengenai alasan tertutupnya laga, Panpel tanpa rasionalisasi menjawab dengan dalih “menjaga keamanan” juga. Oleh karenanya, penulis penting untuk mencatat rekor baru persepakbolaan nasional, bahwa Persebaya adalah klub pertama dan mungkin paling utama yang menjadi incaran strategi politik abnormal sepak bola nasional, yakni mencegah jangan sampai kekuatan yang berada di tribun menjadi mata dan suara kemenangan. Rekor itu bukan bualan, bukan?.
Ancaman Penjegalan
“Transparansi dan kontrol sosial adalah salah satu prinsip dalam negara hukum. Transparansi dibutuhkan untuk memperbaiki kelemahan dalam mekanisme kelembagaan resmi secara komplementer oleh peran serta masyarakat (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin kebenaran dan keadilan.” (Jimly Asshiddiqie dalam Janedjri M. Gaffar, 2012).
Ketidakhadiran pendukung dalam laga memberi konsekuensi pada kemunculan anomali persepakbolaan nasional. Mengapa demikian? Sebab dalam negara hukum, detil semua hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama harus dilihat dan diketahui oleh publik secara luas, tak terkecuali soal sepak bola. Perlu ditegaskan di sini, sepak bola sudah tidak lagi sebatas tontonan yang terlepas dari politik–bermakna strategi atau cara–permainan. Di dalamnya kental sekali keterlibatan berbagai unsur politik baik bersifat supra maupun infra, seperti perputaran antara industri, media, ego kekuasaan, dan tak kalah penting adalah kekuatan suporter untuk memberi power lewat nyanyian dan hentakan mereka kepada tim kebanggaan. Bahkan, unsur politis pun telah ada dan ditemui di pelosok desa saat anak-anak kecil bermain bola, hanya saja mereka belum ingin memahami tetek-mbengek politik, karena sepak bola bagi mereka adalah menggelindingkan bola dengan riang gembira.
Keterlibatan segala unsur politik membuat sepak bola menjadi riskan untuk diselewegkan atau dimanfaatkan oleh pihak penguasa dan pengusaha (baca: PSSI dan mafia). Maka untuk mencegah anomali itu, kehadiran banyak mata di dalam stadion menjadi harga mati yang tidak dapat dihilangkan, bahkan saat klub yang bermain sedang mendapat hukuman tanpa penonton (baca: suporter, bukan media yang meliput). Pertanyaannya, bagaimana jika klub tidak sedang mendapat sanksi akan tetapi laga resmi digelar tanpa penonton? Jawabannya seperti yang ditulis oleh Albert Camus, bahwa “Pemberontakan tak akan ada atau terjadi tanpa ada perasaan (feeling) bahwa entah di mana dan entah bagaimana, seseorang itu merasa benar.” Sampai sini, penulis meyakini jikalau ketidaksepakatan kepada aturan mengenai laga tanpa penonton adalah benar, sebab sejauh yang penulis pahami, bahwa sanksi–termasuk yang digelar tanpa penonton–dalam laga resmi dapat ditimpakan apabila –tidak jauh berbeda seperti pernyataan FIFA mengenai sanksi kepada beberapa timnas dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2018–“…for unsporting conduct of fans in relation to insulting and discriminatory chants…” Itu berarti, alasan keamanan yang digunakan untuk mencegah kehadiran Bonek dalam laga melawan PSBI dan Persinga merupakan paradoks sepak bola yang cacat dalam kacamata aturan resmi.
Akhirnya penulis haqqul yaqin, bahwa sekencang apapun upaya pihak yang ingin menjegal Persebaya dan Bonek, tetap saja cultural chains (ikatan kultural) antar keduanya tidak mungkin bisa berakhir. (*)
*) Ferhadz Ammar Muhammad, Kalijaga Class Bonek Jogja