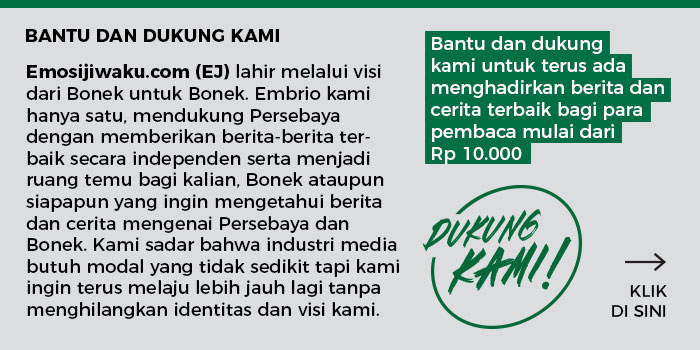“Age is just a number. I feel like a young boy.” (Cristiano Ronaldo)
Inspirasi
Bagi Ronaldo –pesepakbola yang kemarin baru saja membuat rekor sebagai pencetak hattrick tertua sepanjang sejarah pagelaran Piala Dunia itu–, bertambahnya usia tidak berarti bertambahnya kerapuhan (tua). Sepak bola tidak sediskriminatif itu. Memang iya dalam beberapa kompetisi usia sangat ditentukan, tapi itu hanya sekedar syarat administrasi keterlibatan pemain, bukan godam justifikasi produktivitas. Mungkin saja penyelenggara suatu turnamen ingin memberi porsi yang cukup bagi pemain usia muda, seperti alasan yang dulu pernah kita dengar sewaktu Mat Halil dianggap ketuaan.
Kita bisa berdebat soal usia relatif pemain sepak bola, tetapi kita tidak akan bisa mengelak bahwa produktivitas pemain tidak melulu diperah oleh angka usia. Ronaldo sudah membuktikannya, kan? Bahkan justru akan bahaya, kalau sampai stigma ‘pemain tua itu bau tanah’ dipertahankan. Pertama, pemain muda cenderung malah leha-leha, akibatnya kayak kasus Federico Macheda –juniornya Ronaldo pas di Old Trafford– yang melambung lalu dihempaskan –pencari nafkah nomaden. Kedua, pemain tua jadi bad mood-an. Untuk kasus ini, saya ingatkan, jangan meniru Roy Keane yang sering frustasi di akhir karir bersama Manchester United, padahal ia masih bugar dan tajam. Lagi dan lagi, itu karena usia dianggap ancaman karir.
Bak mereka di atas, Persebaya saat ini juga demikian. Usia yang semakin bertambah –91 tahun tertanggal 18 Juni 2018– adalah keniscayaan. Kita harus sadar, sepak bola tidak pernah lepas dari tangan Tuhan, meski pemain haram berbicara itu –biar tidak naif. Namun demikian, keniscayaan takdir yang ikut hadir di lapangan bukanlah untuk merubah tekad dan keindahan gocekan. Keberadaannya hanya untuk memberitahu kemapanan pengalaman dan aktualisasi diri, tidak lebih. Justru akan bahaya jika usia selalu dijadikan tembok batas sampai mana bola menggelinding.
Dalam hal ini, Mat Halil tampaknya bisa menjadi prototype, andai tidak ada pembatasan usia di Liga 2 musim lalu. Ia masih tampak bugar; penguasaan bolanya pun bagus; apalagi presisinya, mantap. Sayangnya, ia musti dengan bijak menerima teriakan PSSI yang berulang-ulang menyebut usianya. “…Tapi saya harus berbesar hati,” ucap Mat Halil menanggapi teriakan regulasi PSSI itu. Penuh legowo, bek legendaris Persebaya itu menerima keniscayaan usianya beserta resiko yang dihadapi. Dahsyatnya, Mat Halil melihat itu menggunakan kacamata kritis. Bahwa ia sudah dipensiunkan oleh regulasi usia, itu benar adanya. Akan tetapi, terpuruk dan meninggalkan cinta pada sepak bola bukanlah karakter sang Legenda. Kini, ia sudah menjadi guru, menelurkan talenta terbaik dari SSB miliknya, El Faza.
Satu Organisasi
“Bereskanlah dahoeloe roemah tangga, kemudian menindjau keluar” (semboyan PSSI –doeloe)
Sampai di titik akhir nanti, tulisan ini menjurus pada satu pressing reflection: di usia ke-91, selain sebagai penyemarak, siapkah Persebaya dan komponennya menjadi guru untuk sepak bola Indonesia? Itu saja. Jadi saya harap, pikiran kalian jangan melesat duluan.
Jujur, sebelum menulis tema ini, saya susah tidur berhari-hari. Setiap kali melihat atap kamar, kok rasa-rasanya melihat tiga rumah berjajar. Rumah pertama bertuliskan manajemen, pelatih, dan pemain; yang kedua bertuliskan tribun; dan ketiga bertuliskan pentolan Bonek. Ketiganya –meski berbeda kadar– mampu membuat saya insomnia berhari-hari. Saya pun musti ambil langkah cepat –healing.
Khusus untuk menghilangkan bayangan rumah yang pertama, saya cari obatnya sendiri. Sekedar kalian tahu, saya memiliki rak buku yang berisi artikel-artikel sepak bola. Eh…siapa tahu buku-buku ini bisa mengalihkan perhatian saya dari rumah yang kelihatan tua dan berdebu itu. Lagi asyik membaca, saya menemukan satu kisah sejarah yang hebat dari pemain yang dahsyat. Mungkin salah satu atau salah dua dari kalian pernah mendengar kisah Socrates –yang pemain Brazil lho ya, bukan yang filsuf Yunani. Socrates ini, meski pemain, tetapi juga aktivis yang pro terhadap unsur kemanusiaan dalam sepak bola. Dulu ia bersama kawan-kawannya pernah membuat gerakan yang sangat masyhur sampai sekarang, kita mengenalnya “Corinthians Movement”.
Gerakan ini dahsyat sekali, yakni merombak paradigma internal tim, bahwa semua komponen, baik pemain, pelatih, manajemen, dan suporter berhak memberi masukan terhadap pengelolaan klub meski kadarnya berbeda. Tidak itu saja, di luar lapangan, gerakan yang dikapteni Socrates ini juga senantiasa mendekatkan diri dengan pergolakan negara dan masyarakat, terutama mengenai ekonomi, sosial, dan politik. Dan tanpa saya sadari, Socrates telah menendang bayangan rumah yang menghantui saya berhari-hari itu. “Ini baru legenda,” gumamku.
Sekarang, tinggal mencari solusi dari dua kegelisahan terakhir saya (rumah tribun dan rumah pentolan Bonek). Kalau ini, saya musti berkonsultasi dengan teman-teman Bonek yang berpengalaman. Satu per satu dari mereka yang saya kenal –tidak banyak, yang penting mereka tidak tamak– tak ajak ngobrol. Sewaktu saya mulai rembukan, terutama saat saya bilang “gagasan organisasi”, ternyata respon yang saya dapatkan sangat meninabobokkan: “gak usah aneh-aneh, lur.” kata mereka.
Duh…rasa-rasanya kok jauh lebih aneh jika melulu membiarkan setiap angkringan membicarakan: “Bonek wingi kisruh neng Bantul.” Atau, “Bonek wingi ono sing mati. Tibo teko truk. Salahe sopo gandulan.” Lebih miris, “kok gak sumbut karo julukan kota pahlawane.” Dan banyak lagi. Saya tanya, sekali lagi, lebih aneh mana menyampaikan gagasan satu wadah, atau melulu membiarkan stigma buruk Bonek berkeLIARan di mana-mana? Bagi saya, omong kosong-lah dengan gimmick: Bonek itu kepala semua, tidak punya tangan dan kaki. Sebab setahu saya, sepanjang sejarah, jika massa tidak dididik oleh organisasi yang satoe, maka tidak akan menghasilkan gema, justru hanya terlihat seperti segerombolan serigala pemangsa –Hobbes menyebutnya Leviathan.
Percayalah, apa yang saya tuliskan ini tidak lain adalah pertarungan batin Bonek anyaran yang hendak membuktikan buaian perkataan para Bonek lawas, bahwa Bonek itu suporter yang memiliki visi tidak hanya goyang; dan Bonek musti memiliki identitas perjuangan hidup di dalam dan di luar. Lha kalau memang begitu, mestinya tidak mungkin perjuangan itu bisa lahir dan berhasil tanpa perkumpulan yang terorganisir, bukan? kata Tan Malaka kan begitu. Lantas, kenapa para Bonek lawas tidak memprakarsai satu wadah organisasi bersama? Ah..lagi-lagi apologi yang dibangun pasti karena satu wadah itu sangat mudah dikendalikan dan dikooptasi oleh pihak berkepentingan. Alamak, momok seperti itu bajik tapi tidak bijak. Itu sama halnya menyuruh semua pemain Manchester United berhenti bermain sepak bola hanya karena ada tragedi patah kaki Luke Shaw. Bukan saya menggurui –lagian saya ini masih Bonek anyaran–, melainkan hanya ingin mengaktualisasikan nasihat KH. Wahid Hasyim untuk berpikir menyelidik, atau mengobati sumber penyakit bukan asal gebyah uyah.
Saya meyakini, bahwa kebimbangan –lebih tepatnya ‘malu’– dan pesimistis beberapa orang terhadap usulan organisasi ditenggarai oleh prasangka-prasangka buruk dan tendensi abal-abal yang bercokol kejam di kepala. Saya jadi teringat pada salah satu cerita dari Voltaire –filsuf Perancis yang terkenal lewat quote “saya tidak sependapat denganmu, tetapi akan membelamu mati-matian untuk berpendapat” itu– lewat karangannya berjudul Si Lugu (L’Ingenu). Si Lugu terlahir seperti manusia sebayanya. Ia tumbuh dan berkembang lewat pengalaman dan tempaan guru kehidupan yang bernama ‘cinta kebijaksanaan’. Dalam cerita, terdapat satu dialog bagus saat Si Lugu berdiskusi tentang: apa tolak ukur ‘terbaik’? dan kenapa orang-orang sering berbeda pilihan terhadapnya? Perhatikanlah jawaban Si Lugu, mengalir dan menusuk:
“Ia dianggap baik seperti banyak orang yang sebenarnya tidak patut memperoleh tempat yang didudukinya. Bagaimanapun juga, ini masalah selera. Mungkin selera saya belum terbentuk dengan baik, pendapat saya mungkin keliru. Pokoknya anda tahu bahwa saya terbiasa mengatakan terus terang pendapat saya, atau lebih tepat perasaan saya. Saya curiga bahwa pendapat orang sering dipengaruhi ilusi, mode, atau tingkah sesat. Sedangkan saya berbicara alamiah…”
Tak dinyana-nyana, di saat banyak orang kota meragukan keluguannya, justru oleh penduduk desanya yang sedang diserang oleh perompah, Si Lugu-lah pemimpin perlawanan dan pahlawan desa yang berhasil menyatukan semua golongan. Nasib baik membawanya ke prestise yang tinggi sekali, bahkan menyentuh kursi sang raja. Meski begitu, dasar si Lugu, saat sudah ditawari berbagai kehormatan, kok ya masih saja ingin di bawah, merunduk bersama kekasih dan masyarakat desa. “Ya, andai keluarga besar Persebaya seperti L’Ingenu itu.” tiba-tiba saya berimajinasi andai Bonek –meski sangar dan kritis– ternyata memiliki pikiran yang alamiah, tidak terombang-ambing oleh persepsi ‘riak’ belaka.
Bagi saya, kutipan di atas bisa digunakan sebagai medium otokritik terhadap apa yang kita tempuh. Kasarnya, medium untuk membongkar kebebalan kita yang sering kali terjebak pada isu golongan –aih…macam politisi aja kita ya, sudah pintar memperseksi isu ini. Memang, realitas kita sangat heterogen –banyak sekali karakter manusia bumi di dalam keluarga kita. Meski demikian, dengan kerendahan hati saya katakan, “Bahkan untuk pemberontak yang paling berontak sekalipun, pembenaran atas tindakan mereka itu adalah solidaritas” begitu bisikan Albert Camus dalam The Rebel-nya. Tidak peduli dari golongan mana pun, solidaritas itulah baju kita yang resmi, dan tidak ada solidaritas yang bisa ditawar dengan ‘pilih kasih’.
Sekarang, sudah saatnya berucap “cukup” pada ketegangan internal Bonek, ia sudah cukup mendewasakan; waktunya bilang “stop” pada kematian disebabkan ‘laka/aniaya’ saat menonton Persebaya, ia harus dihentikan segera; dan masanya berkata “mari berkumpul dalam satu naungan organisasi”, ia adalah koentji. Mengapa? Ya karena kita ini mengklaim diri sebagai pemain ke-12. Lha mosok pemain kok tidak ikut organisasi, ya rusak permainannya. Demi menjaga “Efektivitas pola permainan” kalau kata Gus Dur dalam salah satu cuitannya di Kompas.
Sebelum tulisan ini selesai, karena posisi nulis sedang ramai, ada salah satu sedulur yang nyeletuk: “Kalau sudah ada organisasi, pimpinannya siapa?” Dengan santai saya jawab saja, “Ah…gitu saja kamu pikirkan. Yang penting, kumpul aja dulu. Belum kumpulan kok sudah bahas pimpinan. Dasar, kayak politisi senayan!”