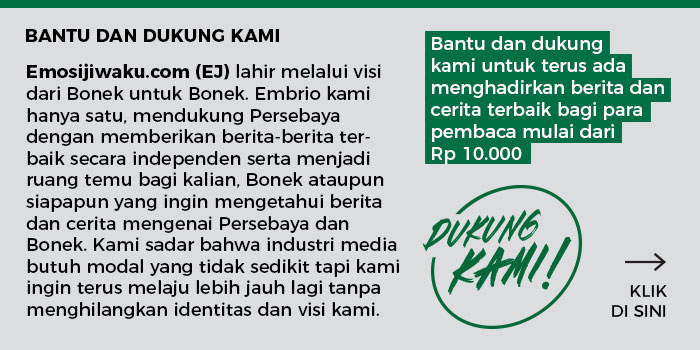Tulisan ini lahir saat tubuh menggigil dan panas dingin setelah menyaksikan tarian Liga Inggris kemarin malam. Di tengah kondisi remuk, saya dihibur oleh dua guru pribadi dari Keputih. Mereka berbincang renyah sekali, mulai rivalitas setan dan unggas sampai perjalan hidup yang keras. Saat itu saya sedang meladeni kluntang-klunting pesan WA dari teman-teman yang mengucapkan ‘selamat atas kekalahan MU’ dan juga sesekali melihat hinaan mereka yang dipajang di story WA. Tidak sengaja saya lihat ada perayaan kecil-kecilan pada salah satu story teman. “Astaghfirullah, perayaan ulang tahun Bonek Campus keempat, to” gumam saya dalam hati. Lha kok, tetiba saya sebagai mahasiswa baru di Surabaya merasa berdosa jika sampai tidak membuat catatan ulang tahun mereka. Dan, mulailah saya menulis ini, sebagai kado sederhana untuk komunitas andalan kita, semoga. Selamat membaca.
Generasi Intelektual
Sekadar saran bagi pembaca, mohon jangan risih dengan diksi ‘intelektual’ di sini. Tenang saja, saya tidak akan berbicara sejarah penyebutan ‘intelektual’ yang ribetnya minta ampun, apalagi kaitannya dengan Skandal Dreyfus dan kemunculan Emile Zola. Lagian, makna intelektual ini sebenarnya sangat sederhana pun tidak berarti melambung tinggi. Lha, adapun anggapan beberapa orang bahwa bahasan intelektual terkesan high class, mungkin saja disebabkan mereka belum memahami total, atau justru kurang bisa membedakan antara intelektual dan pembeo –meminjam istilah dari Moh. Hatta. Percayalah, intelektual itu hanya bisa dimengerti dengan dua tolok ukur, yakni kritis dan dekat dengan semua lapisan, sebagaimana Soedjatmoko (1984) merumuskan, “Yang membuat intelektual menonjol di tengah yang non-intelektual ialah kemampuan berpikir bebas sebagai lawan dari kecenderungan mengikuti saja pikiran orang lain. Konsep berpikir bebas dalam artian ini mencakup pengamatan yang cermat terhadap gejala-gejala di suatu lingkungan, pemahaman tentang sebab gejala-gejala itu dan korelasinya dengan gejala lainnya, dan pada akhirnya perumusan suatu kesimpulan yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain dalam bahasa yang jelas.”
Selanjutnya, perdebatan mengenai posisi kelompok menengah berpendidikan sudah mulai menggema sejak tahun 80-an. Beberapa di antaranya –seperti Bredin (Eyermen, 1996) –berpendapat bahwa mereka berposisi sebagai kelas yang berarti hidup dalam persinggungan dengan kelas-kelas lain yang dominan. Ini sangat mengkhawatirkan, sebab akan mengarah pada teori kelas yang tiada pernah usai sampai sekarang. Saya justru lebih sepakat dengan pendapat Daniel S. Lev yang memposisikan mereka sebagai suatu ‘kelompok’, yakni para pembaharu yang memiliki pengaruh lebih besar daripada proporsi jumlah mereka (Richard Tanter dan Kenneth Young, 1996). Berbeda dari kelas, penggunaan diksi ‘kelompok’ ini lebih renyah sebab terkesan lunak dan tidak terjebak pada aktivitas ‘pertentangan’.
Untung saja Bonek Campus tidak menggunakan diksi kelas, yang berarti ia benar-benar berdiri independen tanpa membawa kepentingan dari pihak mana pun. Kalau toh ia harus berpihak, maka semua itu didasari pemikiran matang dengan berpijak pada prinsip kebenaran dan keadilan universal. Menjalankan itu tentu saja tidak mudah. Butuh tidak hanya sekadar ‘perkumpulan’, melainkan ikatan kolektif yang dipoles dalam penempaan-penempaan.
Sampai sini, saat ikatan kolektif tersebut terpupuk dan berbareng bergerak, ia akan menggumpal dan melahirkan partikel baru yang dinamakan generasi. Makanya dalam sepak bola sering kali ada istilah tersebut, seperti golden generation yang dimiliki Man. United tahun 92, dan generasi emas Persebaya saat juara 87-88. Karl Mannheim dalam The Problem of Generations (1927) mengatakan, “Individuals of the same age, they were and are, however, only united as an actual generation in so far as they participate in the characteristic social and intellectual currents of their society and period, and in so far as they have an active or passive experience of the interactions of forces which made up the new situation.” Jika perkataan Mannheim tersebut kita kontekskan dengan bahasan Bonek Campus, maka bisa diartikan, bahwa suatu kelompok hanya mungkin bisa dikatakan sebagai generasi manakala mampu mengaktualisasikan dirinya oleh penempaan yang terus menerus di dalam masyarakat dan lintasan sejarah. Mereka terus berkecimpung bersama; saling berinteraksi, hingga mampu menciptakan situasi baru berdasar refleksi atas suatu kondisi.
Begitulah, saya meyakini Bonek Campus lahir tidak mungkin berangkat dari ruang kosong. Di balik kaki-kaki yang berdiri tangguh itu, tentu ada canangan target dan program yang sudah tersusun dan menumpuk. Masing-masing anggota pun mengalami penempaan yang luar biasa dalam lintasan sejarah perjalanan Bonek. Kebanyakan dari generasi pertama mereka bahkan berperan langsung dalam upaya memperjuangkan nama besar Persebaya saat dulu tertimpa palu gada. Kini, Bonek Campus telah memasuki usia empat tahun –masa kehidupan sosial yang penuh warna-warni, enerjik, dan seru, namun juga lebih terbuka dalam menyatakan ketidaksukaan terhadap suatu ikhwal.
Tentu dalam perjalanannya, Bonek Campus menghadapi rintangan dan menjadi sorotan. Namun demikian, sebab saya tidak mengikuti perkembangan internal, maka urusan rintangan biarlah anggota Bonek Campus yang akan menceritakan. Kapasitas saya sebagai pihak luar hanya menyoroti eksistensi mereka. Tolok ukur memahami itu sederhana, yakni dengan meneropong kinerja Bonek Campus berkaitan dengan esensi kehadirannya di tengah keluarga besar Bonek. Sekali lagi, ini pandangan saya dari pihak luar –suatu pandangan yang bisa direfleksikan, disimpan, atau dibaca sebagai catatan saja. Terlepas dari itu, saya berani menjamin, tidak hanya saya yang gelisah terhadap orientasi Bonek Campus. Ke mana arah geraknya? Apa fungsi keberadaannya? Dan apa program produktifnya?
Sederhana, dengan nama campus yang melekat di belakang nama Bonek, tentu komunitas ini dituntut untuk lebih menampilkan sisi intelektualisme meski diejawentahkan lewat bahasa yang harus mudah dimengerti oleh publik secara keseluruhan, entah apa pun mediumnya –bisa diskusi langsung, advokasi, karya tulis, atau silaturrahim ilmiah lainnya, ya sesekali agenda ceremonial tiadalah mengapa. Namun, alih-alih mengharap tampilan ‘sang intelektual’ dari Bonek Campus yang komplit, justru yang diharap jarang sekali menampakkan diri. Sampai sini kita sudah memasuki ranah eksistensi ‘fungsi’. Entah anggapan saya ini disebabkan kekurangngopian saya di tempat terbuka atau memang para anggota Bonek Campus pandai menutupi wajah, saya kurang memahami.
Hal yang pasti dari itu semua, bahwa di mana-mana, saat suatu komunitas sudah menempelkan kata yang berartikan ‘intelektual, terpelajar atau semacamnya’, maka secara otomatis segala fungsi ‘kaum intelektual’ melekat atasnya. Fungsi intelektual itu bisa dilihat dari pernyataan Antonio Gramsci dalam bukunya Prison Notebooks yang menjelaskan bahwa fungsi intelektual tidak hanya terletak pada kepandaian retorika dan penampilan, tetapi pada partisipasi aktif sebagai pembangun, organisator, penasihat, serta unggul dalam semangat matematis abstrak. Para intelektual menurut Gramsci harus membongkar jerat yang ada di masyarakat dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui pendidikan partisipatoris.
Oke, katakanlah sekarang kita sudah tahu fungsi dari Bonek Campus. Sekarang tugas selanjutnya, bagaimana Bonek Campus mampu membaca, memilah, dan memecahkan masalah yang dihadapi Bonek secara keseluruhan. Jika kita sepakat bahwa masalah yang dihadapi Bonek adalah image, maka Bonek Campus sepatutnya membuat gebrakan untuk membangun opini publik di ruang terbuka (public sphare). Lha kalau ada kejadian yang menempatkan Bonek sebagai korban, maka Bonek Campus penting untuk berdiri mengadvokasi sesama. Atau misal problemnya ada di internal Bonek sendiri, seperti keorganisasian yang kurang mapan, maka mau tidak mau pendidikan keorganisasian atau kekomunitasan musti digalakkan. Bahkan kalau persoalannya ada di relasi Bonek dan manajemen, tentu Bonek Campus sebagai kelompok menengah kudu bisa menjembatani itu semua. Dan masih banyak lagi lokus yang bisa diperankan oleh Bonek Campus sebagai kelompok menengah yang bisa bergerak ke mana-mana–setidaknya itu yang saya alami sewaktu menjadi kaum menengah di Jogja. Pada titik ini sudah jelas kepada kita, bahwa persoalan utamanya bukan lagi pada modal bergerak, melainkan kemauan dan kehendak.
Akhirnya, salam takdzim dari saya, seorang yang menunggu lokomotifmu berpacu massif dan progresif.