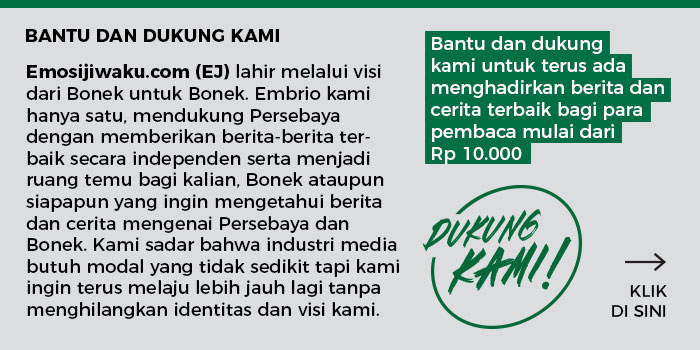Wa bi hadza al-‘ahd alladzi artabithu bika qad Qatha’at ‘ahdi ma’a man ‘adaka. Wa kafani ma fihi dzakhirah li qiyamati (Dengan sumpah/janji yang aku ucapkan, maka telah putuslah janjiku dengan orang selainmu. Sumpah janjiku menjadi simpanan sampai hari kematianku).
Kutipan yang sangat indah dari Laila untuk Majnun, kisah cinta dalam roman padang pasir, tampaknya harus dijadikan iftitah (pembuka). Bukan sebab genre yang sedang ditulis ini mengisahkan kisah asmara pemuda dengan pemudi seperti Laila-Majnun atau Galih-Ratna, melainkan luhurnya niat seorang manusia untuk membuktikan diri di depan mata kekasihnya: tentang hamba Tuhan yang membulatkan tekad untuk menantang segalanya tanpa peduli banyaknya ancaman masalah, bak Majnun yang tak menghentikan langkah di tengah gurun dengan sedikitnya oase ‘mata air’; tentang sosok kurus dengan mata sayu yang memulai perjalanan ke rumah kekasih, laksana Majnun yang terhuyung lari hanya untuk memenuhi janji yang dibuat dirinya meski tanpa sepengetahuan langsung dari Laila; tentang pemilik kaki yang tak bisa berhenti jikalau belum menyapa ‘yang dicinta’; tentang suporter dan tim kebanggaannya, Persebaya.
Adalah Cak Renzha, begitu teman-temannya memanggil, suporter ‘Bajul Ijo’ yang menantang resiko itu. Setiap jalan yang dilewati Renzha adalah jalan sejarah. Setiap rumah yang dijadikan Renzha untuk berteduh merupakan catatan sumpah. Setiap manusia yang ditemui dari Jakarta sampai Surabaya laksana pena yang khusus menulis karya tentang ‘setia’. Ia telah berjalan melampaui omongan orang yang memandang nadzar-nya dengan tanpa saksama.
Ia sudah berlalu meninggalkan kicauan manusia yang sedang sibuk memikirkan keselamatan dan kebenaran sendiri-sendiri dengan memukul manusia lain yang berbeda pikir dan hati. Ia melewati berbagai wilayah dengan ragam penduduknya yang beberapa diantaranya justru diam kala kebanggaan dari usaha mereka dipaksa hilang. Atau lebih jelasnya, ia membuktikan diri kepada kita semua, bahwa wajib hukumnya melaksanakan janji dan sadar jikalau sebuah klub sepak bola tidak hanya tontonan belaka yang terlepas dari akar kultur dan sejarah.
Ya, lewat nazar ‘Jalan Kaki’ yang telah ditegaskan paska hilangnya kaki kedzaliman dari tim berjuluk ‘Green Force’, Renzha telah melakukan perjalanan berjarak 769.000 meter dengan waktu 1.243 jam. Selama itu tercatat 20 kota dan 4 provinsi berhasil dilewati, mulai dari DKI Jakarta sampai pusat Jawa Timur, Surabaya (Emosi Jiwaku, 26/03). Saat di perjalanan, Renzha tentulah tidak hanya diam melihat tanah sembari ditemani lalu-lalang kendaraan dan suara jangrik kala malam.
Di sela istirahatnya, ia tidak berhenti seputar tidur dan menghela nafas sembari makan dan minum untuk mensiasati panas. Justru ia gunakan berbagai dinamika perjalanan untuk mengamati kondisi perjuangan lokal, utamanya terkait sepak bola, dan menyambung tali ‘paseduluran’. Lihat saja update-an dari banyak suporter di daerah-daerah yang dilalui Renzha, dari suporter lokal terkait sampai Bonek ‘Persebaya’ yang memang sudah berpenetrasi di setiap wilayah.
Langkah Renzha demikian penulis artikan lebih berada di jalur interpretasi dari pada harus menyoalkan hukum nazar menurut agama. Selain karena saat ini hukum agama sedang diarahkan pada pembekuan berbentuk monopoli golongan, juga sangatlah naif jika persoalan rasa ‘verstehen’, meminjam Weber, harus dibenturkan dengan hukum yang sangat normatif. Toh kalau nazar Renzha demikian dilihat menggunakan kacamata Islam pun masih khilafiyah (perbedaan pendapat). Sekali lagi penulis katakan, “tidak melihat dari sudut pandang normatif hukum agama”, melainkan interpretasi yang bisa melahirkan ‘ibrah (pelajaran) bagi kita dan dunia sepak bola –dunia yang saat ini sedang jauh dari rasa ‘manusia’ dan lebih menghamba pada ‘mesin dan piala’–.
Meski official Persebaya seakan telah menginterpretasikan tiga hal penting dibalik kisah heroik Renzha, seduluran, branding perubahan Bonek, dan nilai moral untuk melawan narkoba dan miras, akan tetapi penulis masih perlu menambahinya dengan dua hal lagi.
Pertama, jalan Renzha telah mengajarkan bahwa media mainstream memang betul-betul buta. Maaf jika penulis bernada sarkas, akan tetapi tampaknya kata itu yang pantas. Lihat saja saat Renzha masih menikmati perjalanannya, di manakah pemberitaan media?. Persoalan ini bukan sekedar kegilaan akan apresiasi, akan tetapi lebih kepada nalar ‘profit’ yang sampai menghilangkan ‘objektifitas’ terlebih ‘pembelajaran’ bagi generasi. Penulis sangat heran melihat ambiguitas yang terpraktekkan di lingkaran media. Alih-alih menginginkan perdamaian antar suporter, justru ‘join kopi’ antar Renzha dan suporter lainnya dianggap tidak menghasilkan apa-apa. Alih-alih seakan mengatakan bahwa semua editor berharap terhapusnya Bonek dari catatan merah media, justru dengan pongahnya media tersebut seakan mempertahankan adagium Bad news is always a good one (arti mudahnya: berita buruk selalu menjadi hal baik di tangan oknum media pencari untung belaka).
Kedua, kaki Renzha telah menjadi ukuran sejauh mana solidarity chains (tali solidaritas) yang ada di antara suporter dan klub, juga antara manajemen dan pemerintah. Disadari atau tidak, fenomena Renzha telah menjelma menjadi barometer tentang suporter bertipologi solidarity maker (pembuat ikatan solidaritas), meminjam istilah Herbert Feith (1962) tentang kepemimpinan. Tentu sebuah apresiasi layak untuk disematkan, jika memang semua komponen, suporter, manajemen, pemerintah, dan pemegang rekor Indonesia, masih menganggap kaki lebih mulia dari transportasi. Sosok solidarity maker demikian tampaknya masih susah ditemukan jikalau kita semua menggunakan tolak ukur loyal dan moral. Hal ini untuk menghindari tipologi dari terdapatnya sosok yang ditokohkan, akan tetapi tidak pandai mengarahkan sesamanya ke arah manfaati marang liyan (bermanfaat bagi sesama).
Lihatlah sekeliling dunia sepak bola, betapa banyak dari komponen yang masih bangga menjalankan model kolonial berupa monopoli kekuasaan dan devide et impera (pecah belah). Berbeda dengan Renzha, tampaknya loyalitas yang diperlihatkan bukan hanya sekedar omongan pun selalu memperhatikan moralitas ‘kemanusiaan’. Bukti sederhana adalah Renzha berjalan memakai baju Persebaya pun juga mengampanyekan bahaya miras dan narkoba.
Akhirnya lewat dialog imajinatif penulis dengan Renzha, ia berdoa di tengah cerita: Semoga kaki yang melangkah setiap hari selalu melahirkan inspirasi, tangan yang bersentuhan dengan makanan tak pernah lupa berbagi, dan mata yang melihat realita tak buta dengan hal yang sebenarnya ada. Bagi penulis, doa itu menjadi nasehat yang akan menggerakkan terutama suporter di setiap lapisan masyarakat. (*)
*) Ferhadz Ammar Muhammad, Kalijaga Class Bonek Jogja