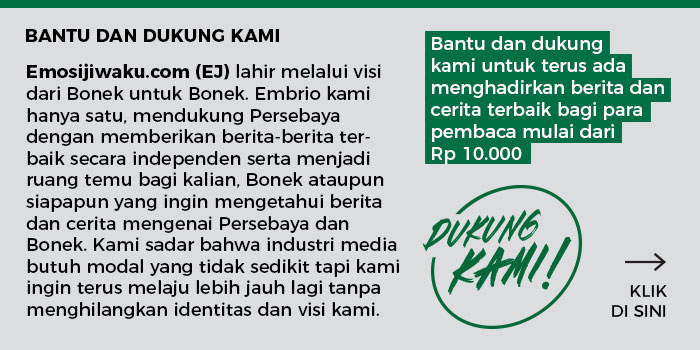“Kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berfikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia sarjana” (Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia)
Penulis awali tulisan ini dengan membayangkan Pram saat melahirkan kata nan indah di atas. Pram tampaknya sedang membayangkan kelakuan manusia yang dengan mudahnya menginjak kemerdekaan orang lain dengan tanpa ampun. Manusia itu tidak mempedulikan protes bahkan jeritan dari tubuh lemah di bawah kakinya. Mereka dengan pongah berdiri laksana kepalanya berada di langit, ambisius. Egonya yang melangit itu hanya mengikuti ambisi dari raja yang ada di atasnya. Mereka tak menyadari jikalau pada dasarnya ada kekuatan besar yang sedang membudaknya, bodoh.
Interpretasi (penafsiran) demikian setidaknya mewakili keadaan penulis saat ini terkait kebijakan tak masuk akal dari PSSI. Ya, bersama dengan manajer Liga 2, federasi yang tampak di residu (baca: luarnya saja) itu bagus telah menghasilkan keputusan menggelikan, terutama terkait batas usia dan pelaksanaan liga. Disebabkan kaidah penulisan mustilah fokus, maka penulis memandang yang terakhir itu (baca: pelaksanaan liga) harus dibahas sesegera mungkin, meskipun yang pertama (baca: batas usia) tak jauh kritisnya sebab menyinggung sang legenda. Baiklah, mari kita bedah logika dan implikasinya jikalau keputusan pelaksanaan liga 2 dijalankan (mengenai keputusan baca Emosijiwaku.com 30/03).
Ancaman?
Saat kecil, penulis diceritakan oleh saudara tentang perjuangan Bonek yang pasti tercatat di lembar sejarah. Waktu itu penulis hanya asyik mendengarkan dengan tanpa menaruh minat penyelidikan. Akan tetapi kini penulis sadar, bahwa bergeraknya Bonek tidak terlepas dari nalar kritis –suatu kesadaran berpikir yang oleh Paulo Freire dianggap sebagai yang terbaik–. Keyakinan penulis itu tidak berangkat dari ruang kosong, melainkan refleksi mudah dari fakta gerakan transformatif Bonek untuk merumuskan kembali keadaan yang tampak ‘belok’ pun ‘bengkok’.
Berbekal dari pengantar di atas, penulis ingin memberi penekanan terhadap petinggi yang semoga membaca tulisan ini, bahwa janganlah heran apalagi tutup telinga jikalau setiap kebijakan sepak bola terlebih menyinggung Persebaya pastilah berhadapan dengan kritisisme Bonek. Heran akan melahirkan sikap pecundang, sedang tutup telinga hanya menghasilkan melipatnya perlawanan. Demikian para tokoh sekelas KH. A. Wahid Hasyim dan Pram menuturkan.
Terkait dengan kebijakan pelaksanaan laga pertandingan liga 2 di hari Senin sampai Kamis, penulis menaruh skeptis. Pertama, potensi penyelewengan oleh mafia. Kita mustilah sadar bahwa sejujurnya mafia masih berkeliaran. Betul perkataan Bang Napi yang pernah didengar sewaktu kecil, yakni kejahatan menampakkan mukanya sebab adanya unsur kesempatan juga. Logika runtutnya seperti ini: ketika PSSI mengetok pelaksanaan liga di hari Senin sampai Kamis yang notabene-nya merupakan masa hari kerja dan sekolah, maka otomatis sudah bisa diprediksi suporter yang datang untuk sekedar meneriakkan nama tim kebanggaan masing-masing akan menurun drastis. Bukan karena mereka suporter amatiran yang hadirnya mood-mood-an, akan tetapi sebab ketidakmungkinan untuk meninggalkan urusan menafkahi atau menghormati amanah belajar dari orang tua secara terus-terusan. Bukan pula sebab mereka sudah dikontrol oleh kekuasaan mesin dan meja sekolah, tetapi seyogyanya semua pihak sadar bahwa rasa kepemilikan pastilah berdasar dari kebutuhan dan kebijaksanaan, sebagaimana kontrak sosial menjelaskan. Selanjutnya, karena absennya banyak suporter di lapangan, maka juga otomatis tidak efektifnya fungsi suporter sebagai control of football. Dari situ dengan mudahnya, secara sadar atau tidak, lapangan sedang dimainkan oleh oknum yang kita sebut: mafia skor.
Kejahatan muncul karena diamnya orang baik -mengutip Ali bin Abi Thalib- tampaknya harus diinterpretasikan lagi sesuai konteks ini. Diam di situ bisa bermakna sepi. Meski ada orang akan tetapi tidak bisa sounding untuk mengontrol keadaan. Akhirnya tindakan di luar batas kemanusiaan di depan mata pun dengan angkungnya berjalan. Atau mungkin karena rasa malu dengan baju palsu, penyelewengan tersebut di laksnakan di bawah meja perjudian, pengaturan skor.
Bagi penulis, suporter patut curiga dengan kebijakan demikian. Tidak dikarenakan hilangnya kepercayaan terhadap federasi, akan tetapi bagaimana mungkin kepercayaan bisa hadir dengan bijaksana dengan tanpa kehati-hatian (ikhtiyath). Suporter juga seyogyanya sadar jikalau fungsi controlling dalam sepak bola hanyalah akan menjadi bahan candaan jika terlepas dari melihat langsung fakta lapangan. Pun paham bahwa penggembosan gerakan sosial tersebut pasti massif dilakukan oleh orang yang mata dan telinganya adalah wujud dari sekedar ‘uang’ dan ‘piala’ –strategi klasik yang berawal dari kolonialisme dan dilanjutkan kapitalisme baru–.
Kedua, ancaman bagi progresifitas klub. Mudahnya yaitu kesebelasan Persebaya akan maju jika tak terbebani dengan urusan-urusan tak produktif, terutama keuangan. Bagaimana bisa membangun stadion berstandar internasional jika untuk menggaji pemotong rumput pun masih kebingungan?. Apakah bisa bermimpi jadi juara tatkala gaji pemain pun tak terbayar segera?. Bukankah naif jikalau hanya mengandalkan nama besar pemilik saham Persebaya sekaligus sponsor padahal kita tak tahu seberapa lama Tuhan memberi titipan harta pada mereka?
Penulis yakin trauma masa lalu saat penunggakan gaji tidaklah ingin dirasakan kembali. Penulis juga sungguh meyakini bahwa manajemen jauh lebih tidak mau jika mengalami penyakit ‘rugi’. Oleh karenanya, sungguh benar jika penolakan terhadap pelaksanaan liga dari Senin sampai Kamis itu digencarkan. Sebagaimana kaidah norma menjelaskan: jikalau beberapa hal buruk berkumpul, maka hindari yang banyak bahayanya. Dan bagi penulis, sangat bahaya jika PSSI masih saja arogansi ditambah jika manajemen pasrah melakukan ‘BUNUH DIRI’. Terkait dengan arogansi PSSI itu, tampaknya kita perlu mendengar pendapat kebanyakan suporter, bahwa kebijakan itu hanya menuruti keinginan media (baca: ANTV dan TV One – Bakrie). Argumen itu sangat beralasan jika kita memahami sebuah adagium: peserta mengikuti pelaksana, sedang pelaksana membutuhkan dana. Dana berasal dari sponsor, sedang sponsor didukung adanya publikator.
Melihat yang demikian, muncul pertanyaan: apakah suporter yang pastinya dirugikan itu diam? Penulis yakin tidak. Melakukan penolakan terhadap keputusan PSSI sebagai federasi tentu bisa dilakukan. Dengan melihat konteks isu ini, suporter yang hak konstitusionalnya merasa dirugikan bahkan bisa membawa perkara ini ke jalur hukum, jika memang kekuatan ‘aksi massa’ perlu tambahan.
Meski statuta PSSI melarang siapapun mulai dari PSSI, anggota, pemain, oficial, serta agen pemain dan agen pertandingan untuk mengajukan perselisihan ke pengadilan negara dan badan arbitrase lainnya, dan lebih mengarah pada penyelesaian masalah oleh yurisdiksi FIFA atau PSSI, akan tetapi atas nama warga negara hukum siapapun itu harus tunduk pada hukum produk Indonesia bukan pasar global. Toh kita semua tentulah paham sebuah asumsi dari ekonomi politik bahwa PSSI sebagai federasi di bawah FIFA merupakan representasi dari logika pasar yang sedang disembah pucuk sepak bola dunia itu. Dari situlah mengapa penulis tidak heran dengan fakta terkait lebih condongnya PSSI untuk menghormati hak siar media dari pada hak siar manusia (suporter).
Akhirnya, nasehat luhur Mahatma Gandhi bisa menjadi refleksi bersama: Adalah di bawah martabat manusia jika seseorang kehilangan kepribadiannya dan menjadi tidak lebih daripada sebuah roda gigi pada mesin. Bahwa orang bekerja bukan berarti menuhankan alat produksi. Bahwa orang belajar bukan lantas mendewakan teks normatif yang tampak sangar. Dan, bahwa meski PSSI butuh dana, tapi tidaklah lantas dengan pongah membunuh klub dengan segala komponennya hanya untuk mengejar proposal bernama ‘siaran media’.
*) Ferhadz Ammar Muhammad, Kalijaga Class Bonek Jogja