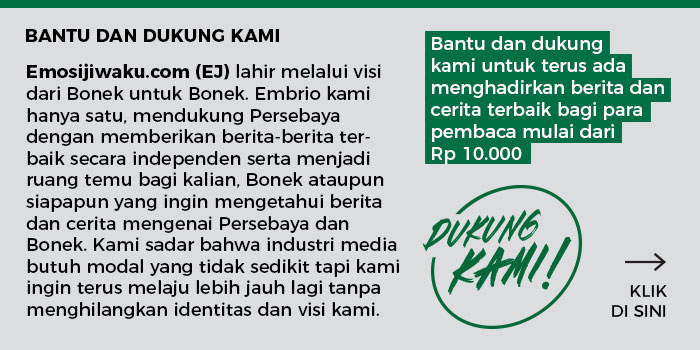“... Saya katakan sementara waktu, karena diktator menyalahi peradaban, menekankan kemauan orang-seorang atau segolongan kecil kepada orang banyak, dengan tidak ada kontrolnya. Perasaan adab dan keadilan, yang hidup di dalam jiwa manusia, suatu waktu akan berontak terhadap diktator, seperti terbukti di dalam sejarah segala masa.” (Moh. Hatta, 1951)
Awalnya, penulis mengira bahwa masa paling susah di lapangan hijau Indonesia adalah tahun saat IPL vis a vis ISL. Penulis pikir bahwa hal yang paling menguras tenaga pecinta sepak bola tanah air yakni kerusuhan antar suporter. Dan penulis membayangkan bahwa kemelut yang paling memuakkan dalam sejarah sepak bola yaitu pertandingan gajah. Seiring perjalannya, asumsi yang menjadikan ketiga hal itu sebagai ‘biang-kerok’ dan penyakit sepak bola Indonesia, nyatanya tidak menjadi sebab yang signifikan.
Era IPL dan ISL harus diyakini sudah selesai. Chant-chant rasis yang menjadi api pertengkaran antar suporter mulai dianggap basi. Begitupun sepak bola gajah juga tampaknya telah sadar diri. Namun, sepak bola baik liga maupun timnas Indonesia masih saja begini: tidak meraih prestasi namun berlagak meninggi. Lantas apa penyebab utamanya? Mari bersama kita cari jawabannya dengan mengukur hubungan empat komponen dalam penyelenggaraan sepak bola, yakni 1) PSSI, 2) Manajemen, 3) Pemain, dan 4) suporter. Oleh karena dalam penulisan harus fokus, maka penulis akan menggunakan medium salah satu klub sepak bola saja, yakni Persebaya. Bukan karena penulis adalah bagian dari suporter klub berjuluk ‘Bajul Ijo’ itu, melainkan sebab tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa Persebaya telah mengalihkan perhatian pecinta sepak bola Indonesia, terutama aksi suporternya untuk mengembalikan kejayaannya. Sebagaimana ilmu komunikasi menurut Carl I. Hovland (dalam Effendy, 1986) ada istilah ‘transmisi stimulus’, maka Persebaya telah memberi rangsangan kepada pecinta sepak bola Indonesia untuk melihat kulit bundar tidak hanya dari luar, melainkan terlibat penuh untuk merubah keadaan.
Sebagaimana falsafah Jawa berkata ojo rumongso bisa nanging sing biso rumongso, musti disadari sebagai masalah kolektif, bahwa sepak bola nasional kembali diguncang permasalahan. Bukan dalam hal prestasi yang semua pihak tampaknya sudah tidak mempertanyakan lagi. Bukan pula mengenai mafia sepak bola, meskipun kelompok hitam itu pastilah ikut campur. Akan tetapi fakta bahwa sepak bola sedang berhadapan dengan dua masalah besar, yakni media dan nalar ‘dikte’ pengurus sepak bola Indonesia, telah memasuki domain represi (kekerasan) eksistensi.
Jika menggunakan teori Barrington Moore (1976), perubahan sosial ke arah yang lebih modern bisa dicapai dengan menggunakan banyak cara, mulai jalur yang demokratis sampai dengan kekerasan diktatorial. Pemilihan kepada salah satu model politik itu tergantung pada penyikapan terhadap kebutuhan ekonomi. Untuk mengejar prestise sebagai ‘negara digdaya ekonomi’, setiap pemimpin negara melakukan cara-cara politik sendiri-sendiri, bisa pemaksaan juga penyerapan aspirasi. Apa yang dipaparkan oleh Moore mengenai perubahan sosial di atas menurut penulis bisa dijadikan pisau penyelidikan untuk membaca gaya kepemimpinan yang dipraktekkan oleh PSSI. Sebab di satu sisi harus diakui bahwa PSSI merupakan organisasi yang tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan ekonomi sebagai syarat transisi kemajuan sepak bola. Tetapi di sisi lain, sepak bola Indonesia musti tidak dicerabut dari akar tradisi lewat tangan-tangan industri, utamanya media televisi.
Penulis sadar-seperti Moh. Hatta menyadari-, bahwa dalam teori manajemen organisasi-termasuk berbentuk federasi-dikenal juga tipologi kepemimpinan besi, akan tetapi itu pun untuk normalisasi keadaan dengan syarat kebijakan yang dikeluarkan tetap masuk akal. Pertanyaannya, apakah akal kita harus dipaksakan menyetujui pendapat yang akan membunuh klub kecintaan? Bagaimana mungkin akal dituntut menerima kebijakan usia dengan dalih regenerasi, jika legenda klub dipaksa berhenti? Bukankah negara-negara yang terkenal sepak bolanya juga masih memberi ruang bagi pemain tua untuk mendampingi yang muda?. Sampai sini penulis harus berkata, bahwa PSSI sedang ‘gagal paham’ kebijaksanaan dalam iktikad kemajuan. Bahwa sepak bola Indonesia dengan tanpa aspirasi dan logika massa, hanya akan melahirkan ‘orde dikte’, yakni sistem, tatanan, atau peraturan yang melulu menyuruh tanpa boleh bertanya terhadap kebijakan apalagi menolaknya.
Melihat Kebijakan
Jika dikontekskan dengan logika gotong royong, kebijakan hanya bisa diambil dengan mekanisme rembuk atau musyawarah. Itu artinya, Indonesia tetap menempatkan penyerapan aspirasi dari komponen bawah untuk membuat setiap kebijakan. Tradisi luhur para sesepuh itu tak lapuk jika dikontekskan pun dikontekstualisasikan. Sayangnya seiring perkembangan waktu, para pemuka-dalam hal ini adalah PSSI juga manajemen-tidak selalu menjadikan ragam pendapat sebagai penguat kebijakan agar dapat legitimate (diakui oleh masyarakat).
Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa sepak bola Indonesia sedang diramu oleh PSSI sesuai nalar kemajuan bermain dan profesionalitas pengelolaan. Sekilas prinsip yang tertuang dalam statuta PSSI tersebut terkesan normal dan memiliki progres baik untuk sepak bola Indonesia. Akan tetapi celakanya-tanpa disadari-, iktikad baik PSSI malah menimbulkan masalah baru, yakni pengejaran akan status ‘maju’ dengan tidak menghiraukan kultur yang dibangun oleh para komponen sepak bola Indonesia sepanjang sejarah. Hal ini bisa dilihat dari fakta tentang kebijakan PSSI yang kerap kali menimbulkan kegaduhan. Seperti kebijakan mengenai Liga 2 yang memupus catatan Indonesia untuk mencetak legenda-legenda, sekaligus menghantam hak ‘humanistik’ suporter.
Mengingat sepak bola Indonesia adalah anak kandung dari sejarah dan budaya, maka segala kebijakan ke arah pembenahan haruslah menyerap sejarah dan budaya yang ada. Secara gamblang, dua unsur penting itu tampaknya bisa dilihat dari dua hal utama, yakni suporter dan legenda klub. Hal ini linier dengan pendapat Antony Sutton dalam wawancaranya oleh salah satu media. Selain Sutton menegaskan identitas sepak bola Indonesia sangat kuat unsur penghormatan kepada legenda hidup sebuah klub, ia juga menaruh perhatian khusus kaitannya dengan suporter, terutama saat ia menyaksikan heroiknya Bonek saat mengawal Persebaya (14/02).
Pendapat Sutton di atas penulis interpretasikan sebagai dua hal esensial. Pertama, sepak bola Indonesia tetap harus berjalan sesuai dengan keunikannya. Meski demikian, tidaklah bijak jika menganggap hal itu sebagai antipati terhadap perbaikan dan perubahan. Masih terdapatnya konflik vertikal dan horizontal di sepak bola Indonesia adalah bukti perlunya pekerjaan baik di setiap lini itu. Kedua, kebijakan sepak bola Indonesia musti terlepas dari sentimen politis pribadi apalagi nalar picik ekonomi. Selama ini banyak pakar yang melihat PSSI sebagai perkumpulan yang didominasi kalangan politisi dengan tipologi kepemimpinan elitis, baik militeristik maupun birokratik. Elitis tadi membawa konsekuensi kepada kemungkinan adanya monopoli dan akumulasi keuntungan-sebagaimana Gaetano Mosca (1858-1941) menjelaskan. Di era Edy Rahmayadi ini, monopoli kekuasaan sekilas tidak terlihat jelas, akan tetapi dapat dirasakan saat mengamati lahirnya kebijakan. Hal itu bersumber dari asumsi penulis bahwa termasuk monopoli adalah sikap penguasa yang tidak mendengarkan aspirasi massa. Meski demikian dengan bijak penulis musti bersyukur jika dalam perjalanannya sudah ada revisi dan klarifikasi terkait agenda liga (berita rapat Exco PSSI, 05/04).
Mengenai akumulasi keuntungan, media televisi menurut Habermas (1986) dalam domain public sphere (ruang publik) sangatlah berpengaruh kuat. Media yang awalnya sebagai tempat transfer dan dialektika wacana, berubah menjadi ruang komersil untuk mengeruk keuntungan lewat frekuensinya. Dalam hal ini, Persebaya di Liga 2 yang dikenal merupakan klub dengan banyaknya basis pecinta dapat menjadi medium akumulasi keuntungan di ranah tontonan sepak bola. Selain Persebaya, berdiri Persib di Liga 1 dengan keuangan yang tidak diragukan lagi jumlahnya. Dua tim tersebut penulis anggap paling menjual karena dua hal, yakni peminat yang membludak, Persebaya dengan fakta menarik perjalannya dan Persib dengan iklan-seperti Habermas mengatakan-yang terpampang begitu banyak. PSSI tentu tidak ingin melewatkan ini. Maka media televisi dijadikan partner untuk menampilkan laga kedua klub itu di setiap liga. Persib di sekitar hari Sabtu-Minggu, sedang Persebaya di Senin-Kamis.
Sekali lagi penulis tidak menampik kebutuhan PSSI untuk mendanai federasi, akan tetapi mustilah dengan melihat kebaikan bersama yang tentu melibatkan suporter klub juga. Dengan demikian, penulis akan mengapresiasi langkah PSSI untuk tetap melaksanakan Liga 1 dan Liga 2 di hari-hari libur, dan untuk penampilan di televisi masih tetap seperti format semula (Sabtu-Minggu di Liga 1 dan Senin-Kamis di Liga 2).
Akhirnya, mari sejenak mendengarkan nasihat UEFA sembari berharap semoga PSSI mengingat luhurnya spirit pendirian di tahun 1930. “Dalam dunia yang ideal klub sepakbola akan secara terstruktur dan diatur dengan cara yang memprioritaskan tujuan olahraga di atas aspek keuangan. Selain itu, semua klub akan dikontrol dan dijalankan oleh anggotanya – misalnya pendukung – sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi” (Strategy Document, UEFA). (*)
*) Ferhadz Ammar Muhammad, Kalijaga Class Bonek Jogja